Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Mengandung Cacat Bawaan Konstitusi
 Dr. Asrullah, S.H., M.H
Dr. Asrullah, S.H., M.HOleh: Dr. Asrullah, S.H., M.H. (Pakar Hukum Tata Negara & Senior Counsel Law Firm Rudal and Partner)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pengujian kumulatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, telah menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Substansi putusan MK tersebut memberikan guidance bersifat inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap tiga pasal dari dua undang-undang a quo. MK menyatakan bahwa:
“Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Setelahnya, dalam waktu paling singkat dua (2) tahun atau paling lama dua tahun enam bulan (2,5 tahun) sejak pelantikan anggota DPR dan DPD atau Presiden/Wakil Presiden, diselenggarakan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.”
Permasalahan inti dari putusan ini bukan semata pada pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, melainkan pada ketentuan jeda waktu antara keduanya. MK secara hukum telah mewajibkan adanya masa transisi antara pemilu nasional dan lokal dengan rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan. Ketentuan inilah yang menimbulkan cacat bawaan terhadap konstitusi, khususnya Pasal 22E UUD NRI 1945.
Pasal 22E ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945 secara expressis verbis dan limitatif menyatakan bahwa:
(1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.
(3) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.
Jika dikaji melalui pendekatan tafsir gramatikal, sistematis, dan historis—yang juga sering digunakan MK dalam memutus perkara—maka jelas bahwa ketentuan masa jeda tersebut justru paradoks, diametral, dan menyimpangi amanat Pasal 22E UUD NRI 1945.
Pasal 22E ayat (1) mewajibkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung dengan periode lima tahunan. Jika terdapat jeda dua tahun hingga dua setengah tahun, maka masa jabatan anggota DPRD akan melewati batas konstitusional lima tahun, yang jelas bertentangan dengan ayat tersebut.
Pasal 22E ayat (2) bermakna bahwa pemilu untuk memilih anggota DPRD termasuk dalam rezim pemilu yang wajib dilaksanakan secara langsung dan tidak boleh melebihi lima tahun masa jabatan. Sedangkan Pasal 22E ayat (3) mengatur bahwa peserta pemilu adalah partai politik, sehingga pengisian jabatan harus dilakukan melalui mekanisme elected official, bukan selected official. Konstitusi tidak membuka opsi atau alternatif perpanjangan masa jabatan bagi pejabat publik melalui penunjukan.
Dengan demikian, keabsahan dan legitimasi jabatan anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, serta DPRD hanya sah apabila diperoleh melalui pemilihan umum secara langsung. Maka, ketentuan masa jeda dalam putusan MK justru bertentangan dengan konstitusi.
Secara historis, ketentuan dalam Pasal 22E adalah bentuk koreksi terhadap praktik pengisian jabatan politik yang tidak demokratis pada masa lalu, serta sebagai jaminan terhadap prinsip bottom-up sovereignty, di mana rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.
Masalah ketatanegaraan berikutnya yang timbul adalah: bagaimana status jabatan anggota DPRD dalam masa jeda tersebut? UUD NRI 1945 tidak membuka ruang untuk masa jabatan di luar siklus lima tahun. Maka, perlu adanya formulasi jelas agar tidak menimbulkan krisis legitimasi konstitusional.
Mahkamah Konstitusi perlu menyusun suatu Constitutional Compliance, yaitu penjelasan resmi kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) mengenai arah dan implementasi putusan a quo. Ini penting agar tidak terjadi penyimpangan dan kekosongan hukum. Selain itu, perlu ada Constitutional Engineering dalam revisi UU Pemilu dan UU Pilkada untuk menjaga konsistensi dengan UUD NRI 1945, serta memastikan marwah MK sebagai lembaga yudisial konstitusional tetap terjaga.
Terkait posisi MK dalam membuat norma baru, secara teoritik, MK adalah Negative Legislator—yakni hanya menyatakan ketentuan undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi, tanpa membuat norma baru. Namun dalam praktik modern peradilan konstitusi, telah berkembang paham judicial activism, yang membolehkan MK menyusun norma atau panduan konstitusional tertentu.
Contoh klasiknya adalah perkara Marbury v. Madison di Amerika Serikat, yang menjadi landmark decision karena mengakui kewenangan pengadilan konstitusional dalam membentuk tafsir dan norma baru. Namun demikian, tindakan tersebut tetap tidak boleh menyimpangi ketentuan konstitusi, apalagi secara vis-à-vis bertentangan dengan UUD 1945.
Inilah akar dari problematika dalam putusan MK terkait pengujian UU a quo. Sebagai penjaga konstitusi (The Guardian and Protector of the Constitution), MK seharusnya lebih bijak menggunakan kearifan konstitusionalnya (constitutional wisdom), bukan menjadikan final and binding sebagai alat pemaksa terhadap para stakeholder bernegara.
MK seharusnya mengingat asas hukum:
“Lex clara non sunt interpretanda”
Jika suatu ketentuan hukum sudah jelas dan tidak menimbulkan keraguan, maka tidak perlu ditafsirkan lebih lanjut.
Karena justru, ketika ditafsirkan secara berlebihan, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru. (*)
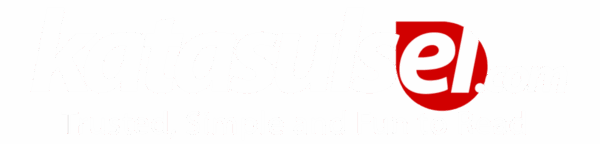


















Tidak ada komentar