
Kendati begitu, angka proporsi masih menunjukkan tantangan: 601 kasus dari total sasaran pemeriksaan menunjukkan positivity rate yang belum ideal. Ini bisa merefleksikan dua kemungkinan—entah cakupan skrining masih terbatas, atau memang transmisi komunitas masih berlangsung aktif.
RSUD Siwa bahkan harus mengaktifkan empat kamar isolasi khusus untuk merespons situasi ini. “Kami siapkan ruang isolasi agar mencegah transmisi nosokomial, karena TB sangat rentan menyebar di ruang tertutup,” ujar dr. Gusaidi.
Pendekatan Sidrap terlihat lebih strategis secara struktural. Selain pemanfaatan alat diagnostik berbasis molekuler, kabupaten ini juga menyasar TB laten yang kerap luput dari radar. Upaya menggandeng institusi pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kampanye berkelanjutan menunjukkan bahwa penanggulangan TB bukan semata urusan Dinas Kesehatan, tapi agenda sosial-kultural bersama.
Adapun di Wajo, langkah-langkah awal seperti pemberian Terapi Pencegahan TB kepada kelompok rentan mulai diterapkan. Namun tantangannya kini terletak pada ketahanan sistemik: konsistensi program, penguatan pelaporan, hingga kesadaran masyarakat yang harus dibentuk tidak hanya lewat penyuluhan, tapi juga pemberdayaan lokal berbasis adat dan komunitas.
Secara nasional, beban TB Indonesia masih di antara yang tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, keberhasilan daerah seperti Sidrap memiliki daya ungkit penting terhadap target eliminasi TB pada 2030.
“Sidrap bukan episentrum, tapi kalau semua kabupaten bergerak dengan kecepatan dan metode yang sama, kita tidak sedang bermimpi,” tutup Dr. Ishak.
Sebaliknya, Wajo menunjukkan bahwa di banyak wilayah, perjuangan masih berada pada fase awal. Antara angka dan aksi, antara pengetahuan dan kebiasaan, antara sistem dan kenyataan sosial. TB, lebih dari sekadar penyakit, adalah potret rapuhnya struktur hidup sehat dalam masyarakat—dan membenahinya tak bisa setengah hati.(*)
Editor: Edy Basri
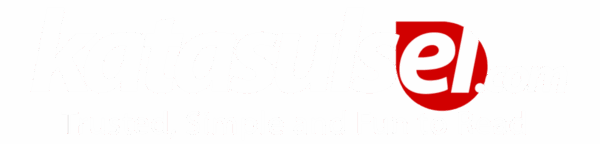
















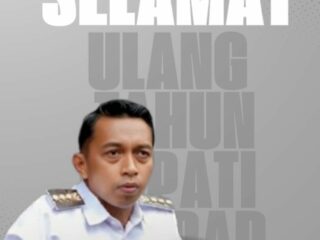

Tidak ada komentar