
Oleh: Muh. Izwan
Visi besar Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045—ketika republik ini genap berusia seratus tahun—kian sering digaungkan dalam berbagai forum nasional maupun internasional. Pemerintah, akademisi, hingga pelaku bisnis memproyeksikan optimisme bahwa Indonesia akan masuk lima besar ekonomi dunia, dengan pendapatan per kapita diperkirakan lebih dari 20 ribu dolar AS. Sebuah mimpi besar yang tentu saja pantas untuk dikejar.
Namun, di balik euforia yang terus digulirkan, ada pertanyaan mendasar yang belum mendapat jawaban tuntas: apakah sistem pendidikan nasional kita benar-benar mampu melahirkan generasi emas yang siap bersaing di panggung global? Pertanyaan ini penting, sebab sejarah dunia menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi, stabilitas sosial, dan kekuatan suatu bangsa pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia. Jepang, Korea Selatan, Singapura, hingga Finlandia membuktikan bahwa pendidikan yang berorientasi pada kualitaslah yang mengangkat mereka dari keterpurukan menuju kemajuan. Sebaliknya, tanpa pendidikan yang kokoh, bonus demografi hanya akan menjadi bencana demografi.
Indonesia diproyeksikan memasuki masa bonus demografi pada 2030–2040, ketika 64 persen penduduk berada pada usia produktif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 196 juta jiwa. Secara teoritis, kondisi ini menjadi peluang emas: mayoritas penduduk adalah tenaga kerja produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan inovasi, dan mempercepat transformasi industri. Namun realitasnya, indikator kualitas pendidikan justru menunjukkan alarm bahaya. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 66 dari 81 negara dalam literasi membaca, 65 untuk matematika, dan 68 untuk sains. Artinya, sebagian besar siswa Indonesia belum menguasai keterampilan dasar yang menjadi fondasi inovasi.
World Bank (2022) bahkan memperingatkan bahwa 70 persen anak usia 10 tahun di Indonesia mengalami learning poverty—ketidakmampuan memahami bacaan sederhana. Jika keterampilan dasar saja belum kokoh, bagaimana mungkin mereka mampu beradaptasi dengan tantangan kompleks abad ke-21 seperti kecerdasan buatan, green economy, atau industri berbasis digital? Tanpa reformasi pendidikan, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi: ledakan pengangguran, meningkatnya kriminalitas, dan potensi instabilitas sosial. Alih-alih menjadi mesin pertumbuhan, generasi muda justru berisiko menjadi generasi yang “hilang” (lost generation).
Pendidikan di Indonesia masih diwarnai ketimpangan yang tajam. Data Kemendikbudristek 2023 menunjukkan lebih dari 40 ribu sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) mengalami kekurangan guru dan fasilitas. Di kota-kota besar, anak-anak menikmati sekolah dengan akses internet cepat, laboratorium modern, bahkan pembelajaran berbasis artificial intelligence. Sementara itu, di pelosok Papua, Nusa Tenggara Timur, atau Maluku, masih ada sekolah dengan bangku reyot, atap bocor, dan guru yang harus merangkap mengajar beberapa kelas sekaligus.
Pandemi Covid-19 semakin memperlebar jurang tersebut. Survei UNICEF (2021) menyebutkan bahwa 1 dari 3 siswa di pedesaan tidak mampu mengikuti pembelajaran daring akibat keterbatasan akses internet dan perangkat. Kondisi ini menimbulkan jurang digital yang berpotensi melahirkan ketidakadilan sosial dalam jangka panjang. Jika ketimpangan ini dibiarkan, maka gagasan Indonesia Emas hanya akan menjadi “Indonesia Jawa-Sumatra Emas”, sementara daerah-daerah 3T tetap tertinggal.
Sejak 2009, konstitusi mengamanatkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Pada 2025, anggaran pendidikan diproyeksikan mencapai Rp660,8 triliun—salah satu yang terbesar di Asia. Namun ironi terjadi: mutu pendidikan kita justru stagnan. Studi Bank Dunia (2022) mengungkap bahwa efektivitas belanja pendidikan di Indonesia masih rendah. Sebagian besar anggaran terserap untuk gaji dan tunjangan pegawai, sementara alokasi untuk peningkatan mutu guru, riset, serta pengembangan kurikulum relatif kecil. Selain itu, sistem evaluasi pembelajaran lebih fokus pada capaian administratif ketimbang kualitas hasil belajar. Akibatnya, dana besar yang digelontorkan negara belum berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi siswa. Pertanyaan yang menggelitik: Apakah kita sedang membiayai pendidikan, atau sekadar membiayai birokrasi pendidikan?
Tantangan lain datang dari ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Revolusi industri 4.0 dan transformasi digital menuntut keterampilan abad ke-21: literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan problem solving. Namun, kurikulum nasional masih terlalu menekankan hafalan. Ujian sering kali mengukur daya ingat, bukan kemampuan berpikir kritis. Tidak heran, banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang dinilai tidak siap menghadapi dunia kerja.
Laporan Asian Development Bank (2023) memperkirakan bahwa dalam 20 tahun mendatang, 40 persen pekerjaan di Indonesia berisiko tergantikan otomatisasi. Tanpa keterampilan baru, jutaan lulusan berpotensi kehilangan daya saing. Tidak hanya industri manufaktur, profesi di bidang jasa seperti akuntan, jurnalis, hingga tenaga administrasi pun mulai terancam otomatisasi. Pertanyaannya, apakah sistem pendidikan kita sudah menyiapkan siswa untuk pekerjaan yang bahkan hari ini belum ada?
Banyak negara yang berhasil melakukan lompatan besar berkat reformasi pendidikan. Korea Selatan pada 1960-an memiliki PDB per kapita hanya sekitar USD 80, lebih rendah dari Indonesia. Namun mereka melakukan investasi besar-besaran dalam pendidikan, terutama sains dan teknologi. Hasilnya, dalam tiga dekade, Korea menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dengan industri teknologi maju. Finlandia melakukan reformasi pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan guru dan kurikulum yang menekankan kreativitas serta pembelajaran berbasis masalah. Hasilnya, Finlandia konsisten berada di papan atas PISA, meskipun alokasi anggaran pendidikan mereka tidak sebesar negara lain. Singapura, negara kecil di Asia Tenggara, sukses membangun sistem pendidikan yang link and match dengan industri. Pemerintah rutin memperbarui kurikulum sesuai perkembangan global. Tidak heran, tenaga kerja Singapura dianggap salah satu yang paling adaptif di dunia.
Indonesia sebenarnya punya potensi besar untuk meniru model sukses ini. Namun, syarat utamanya adalah konsistensi, keberanian melakukan reformasi, dan keberpihakan politik pada pendidikan berkualitas. Jika Indonesia serius ingin mewujudkan visi 2045, pendidikan harus mengalami reformasi besar. Kurikulum harus berfokus pada literasi digital, sains, teknologi, inovasi, dan pembentukan karakter. Ujian berbasis hafalan harus diganti dengan penilaian berbasis kompetensi. Guru sebagai jantung pendidikan harus mendapat pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan transformasi metode ajar. Tidak ada pendidikan berkualitas tanpa guru berkualitas. Infrastruktur digital harus merata, khususnya di daerah 3T. Internet cepat, perangkat teknologi, dan platform pembelajaran daring harus dihadirkan untuk menghapus jurang digital. Pendidikan vokasi harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sementara perguruan tinggi perlu bermitra dengan dunia usaha agar lulusan siap kerja dan siap berinovasi. Universitas harus menjadi pusat riset, bukan sekadar produsen ijazah. Pemerintah dan swasta harus meningkatkan investasi riset agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen.
Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita yang layak diperjuangkan. Namun, ia bukan hadiah yang datang begitu saja. Generasi emas hanya akan lahir dari sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jika reformasi pendidikan hanya berhenti pada retorika tanpa implementasi nyata, visi 2045 hanya akan menjadi slogan politik. Dunia tidak akan menunggu Indonesia. Negara-negara lain sudah berlari, sementara kita masih sibuk memperdebatkan kurikulum, membagi anggaran, dan mengelola birokrasi.(*)
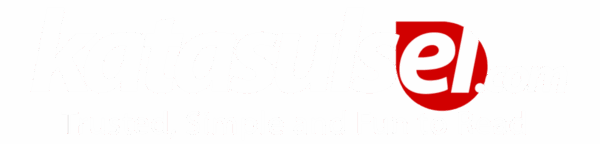


















Tidak ada komentar