Dari Camba-Maros ke Bangkok, Inilah Kisah Panjang “Profesor Penulis” Itu
 Ismail Suardi Wekke (kanan)
Ismail Suardi Wekke (kanan)Sudah ada contohnya. Dari Manado. Dari Wamena. Mahasiswa-mahasiswa itu ia bawa ke Thailand. “Pelan-pelan kita perkenalkan kampus Indonesia,” katanya.
Ismail sadar, dunia sudah global. Tidak ada lagi batas negara yang kaku. Dan mahasiswa Indonesia tidak boleh hanya jadi penonton. Mereka harus ikut bicara, ikut menulis, ikut tampil di forum internasional.
Yang membuat Ismail berbeda adalah kebiasaannya menulis. Hampir setiap hari. Jurnal, opini, laporan riset.
Semua ia tuangkan di kertas atau layar laptop. Ia percaya, menulis adalah cara paling nyata untuk meninggalkan jejak.
“Kalau tidak ditulis, ilmu akan hilang bersama kita,” katanya.
Menulis juga yang membawanya berkeliling dunia. Artikel-artikelnya membuat ia dikenal. Undangan datang karena publikasi. Bukan karena lobi.
Bukan karena jabatan politik. Tetapi karena karya tulisnya dibaca, dirujuk, dan dianggap penting.
Dari Malaysia hingga Eropa, ia berdiri di mimbar akademik. Semua berawal dari tulisan.
Selain mengajar di Pascasarjana STAIN Sorong, Ismail juga aktif di organisasi. Ia pernah menjadi Ketua Hubungan Luar Negeri DPP KNPI. Di posisi itu, ia semakin mengerti pentingnya diplomasi pendidikan.
Ia bukan hanya akademisi di ruang kelas. Ia juga aktivis. Ia tahu cara bicara dengan pemerintah, dengan organisasi mahasiswa, dengan tokoh masyarakat. Dan semua itu ia gabungkan: riset, organisasi, jaringan.
Meski sudah melanglang buana, Ismail tidak pernah melupakan Camba. Ia selalu menyebut dirinya anak kampung. “Saya lahir di Camba,” ujarnya dengan bangga.

Ia tahu, gelar profesor bisa membuat orang silau. Tapi ia lebih memilih menyebut dirinya penulis. Karena dari kecil, ia memang gemar menulis. Karena dari kampung, ia tahu betapa pentingnya pendidikan.
Kisah Ismail penting bukan karena ia profesor. Banyak orang bergelar profesor. Tetapi tidak semua memaknai gelar itu sebagai jembatan.
Bersambung………..
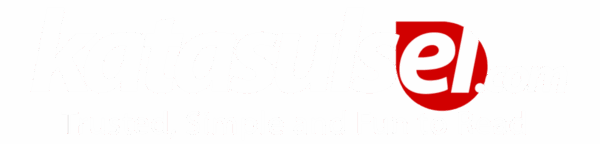
















Tidak ada komentar