Anak Wajo Itu Menggenggam Santunan, Tapi Sesungguhnya Ia Sedang Menggenggam Sisa-sisa Hidupnya
 Anak Wajo Itu Menggenggam Santunan, Tapi Sesungguhnya Ia Sedang Menggenggam Sisa-sisa Hidupnya
Anak Wajo Itu Menggenggam Santunan, Tapi Sesungguhnya Ia Sedang Menggenggam Sisa-sisa HidupnyaIni kisah yang seharusnya tak pernah ditulis. Sebab, tak ada seorang anak pun di dunia ini yang ingin kisah tentang kedua orang tuanya berakhir dengan api, abu, dan amplop santunan.

Oleh: Edy Basri
Air mata saya menetes saat menulis naskah ini. Jujur, awalnya tak sanggup. Tapi ini penting, ini kata hati seorang anak yang benar-benar kehilangan. Beginilah kisahnya.
Pada Selasa siang yang mendung di Makassar—25 November 2025—seorang anak bernama Andi Nirwana, asal Kabupaten Wajo, berdiri membawa sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan digenggamnya seumur hidup: dua amplop santunan kematian.
Satu untuk ayahnya.
Satu untuk ibunya.
Dua amplop.
Dua nyawa.
Dua dunia yang padam sekaligus.

Orang bilang setiap manusia punya hari pertama dalam hidupnya. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa manusia juga punya hari “pertama” menjadi yatim. Dan bagi Nirwana, hari itu datang terlalu cepat, terlalu mendadak, terlalu kejam.
Itu terjadi di Wajo, di sebuah rumah sederhana di Jalan Lembu.
Rumah yang biasanya penuh panggilan ibu menyuruh makan.
Rumah yang biasa dipenuhi wangi kopi buatan ayah.
Rumah dengan dua kursi reyot tempat orang tuanya tiap pagi berbincang hal-hal sederhana yang justru sangat berarti.
Di rumah itu pula, kedua orang tuanya mengambil napas terakhir bersama-sama, dalam kobaran api yang datang tiba-tiba—api yang melahap pakaian, foto, furnitur, dan sebagian hati seorang anak.
Tidak ada yang pernah siap menjadi saksi dari hidup yang patah.
Dan pada malam itu, hidup Andi Nirwana patah di tengah.
Empat hari setelah pemakaman, tubuh Nirwana seperti sekadar berjalan demi kewajiban. Kepalanya berat, tapi langkahnya harus tetap menapak. Ia harus datang ke Makassar menerima santunan.
Empat hari.
Empat malam tanpa tidur lengkap.
Empat malam menatap atap rumah keluarga, memandangi langit yang sama sambil bertanya lirih:
“Ayah, Ibu… kenapa secepat ini?”
Orang bilang waktu menyembuhkan luka.
Tapi tidak ada yang menjelaskan bahwa waktu tidak bisa menyembuhkan luka empat hari.
Dalam empat hari itu, seseorang tidak sedang sembuh.
Ia sedang berusaha sekadar tidak roboh.
Pagi hari ketika berangkat dari Wajo menuju Makassar, ia ditemani seseorang yang kelak sangat ia syukuri kehadirannya: Fariz Athar Malika, pendamping dari Dinas Sosial Wajo.
Nirwana tidak banyak bicara.
Ia hanya menatap jendela mobil, memandangi kebun-kebun, rumah panggung, warung kecil, dan jalan panjang yang terlihat seperti tidak punya ujung.
Dalam bayangannya, ayahnya sedang menyetir mobil tua mereka.
Ibunya duduk di samping, membawa bekal nasi.
Mereka tertawa.
Tapi itu hanya bayangan.
Yang nyata adalah kursi kosong di sebelahnya—kursi yang seharusnya diisi ayah dan ibunya, tetapi hari itu kosong untuk selamanya.
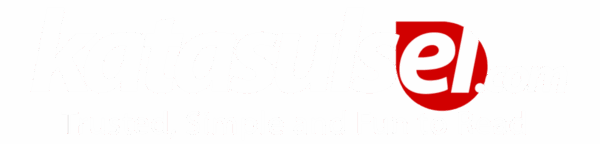

















Tidak ada komentar