Jalan Berdebu Sidrap Itu Masih Ada di Ingatan Syahar, Bahkan Saat Ia Berdiri di Panggung Nasional

Tak banyak yang tahu, di balik senyum tenang Syahar hari itu, tersimpan perjalanan panjang yang ia lalui tanpa keluh—jalan sunyi yang justru membentuknya hingga berdiri di panggung megah itu.

Oleh: Edy Basri
Di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, lampu-lampu sorot menari seperti sedang menandai satu momen yang lebih besar dari seremoni biasa.
Tepuk tangan mengalun, penonton bangkit, kamera menyorot, dan di tengah pusaran itu seorang lelaki berbaju batik ala seorang guru berdiri dengan sorot mata yang lebih tenang dibanding siapa pun di ruangan itu.
H. Syaharuddin Alrif, Bupati Sidrap yang selama ini lebih sering muncul dengan gaya kerja lapang ketimbang gaya formal panggung nasional, menerima Dwija Praja Nugraha—penghargaan tertinggi dari PGRI untuk kepala daerah yang dianggap benar-benar peduli pada dunia pendidikan.

Di panggung itu ia tidak meneteskan air mata. Tidak pula menunjukkan emosi berlebih seperti banyak pejabat yang merasa momentum seperti ini adalah babak puncak dalam hidupnya.
Tetapi jika ada kamera yang bisa menembus isi pikirannya, mungkin orang-orang akan melihat sesuatu yang berbeda: cuplikan masa-masa berat yang tidak pernah ia ceritakan di forum publik, tahun-tahun panjang ketika hidup bahkan tidak memberinya cukup alasan untuk membayangkan bahwa suatu hari ia bisa berdiri di panggung nasional, disaksikan ribuan guru se-Indonesia.
Senyum kecilnya sore itu bukan senyum politisi yang menerima penghargaan. Itu lebih seperti senyum seseorang yang sedang mengingat sesuatu—atau seseorang yang sedang berterima kasih pada masa lalunya yang keras tetapi jujur.
Sebab Syahar datang dari tempat yang tidak pernah menjanjikan jalan mulus bagi siapa pun. Ia lahir di tengah keluarga sederhana, dalam kultur kerja keras yang tidak memberi ruang bagi manja. Di rumah itu tidak ada kalender mimpi pekerjaan besar.
Yang ada hanya pekerjaan harian yang harus selesai. Dan di kehidupan seperti itu, anak-anak tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup tidak menunggu mereka siap. Hidup berjalan, dan mereka harus ikut berlari.
Ia pernah bangun subuh, bukan untuk memberi sambutan atau menyiapkan bahan rapat, tetapi untuk bersiap mengemudi mobil orang.
Bukan mobil mewah, bukan pula mobil perusahaan: mobil yang harus dijaganya seperti milik sendiri meski gajinya jauh dari cukup. Ia pernah mengantar orang dari kampung ke kota, dari pasar ke ladang, dari rumah ke rumah sakit—dan setiap penumpang selalu mengingatkannya pada satu hal: manusia hidup karena saling bergantung.
Menjadi sopir mengajari Syahar banyak tentang ritme hidup masyarakat biasa. Ia tahu suara mesin yang meraung saat tanjakan.
Ia tahu wajah penumpang ketika cemas, ketika senang, ketika punya harapan, atau ketika diam karena memikirkan sesuatu yang berat. Dari kursi sopir itu, ia belajar bahwa hidup bukan tentang cepat sampai, tetapi tentang bagaimana memperlakukan perjalanan.
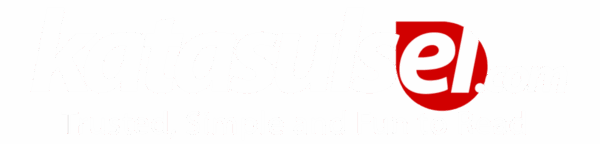








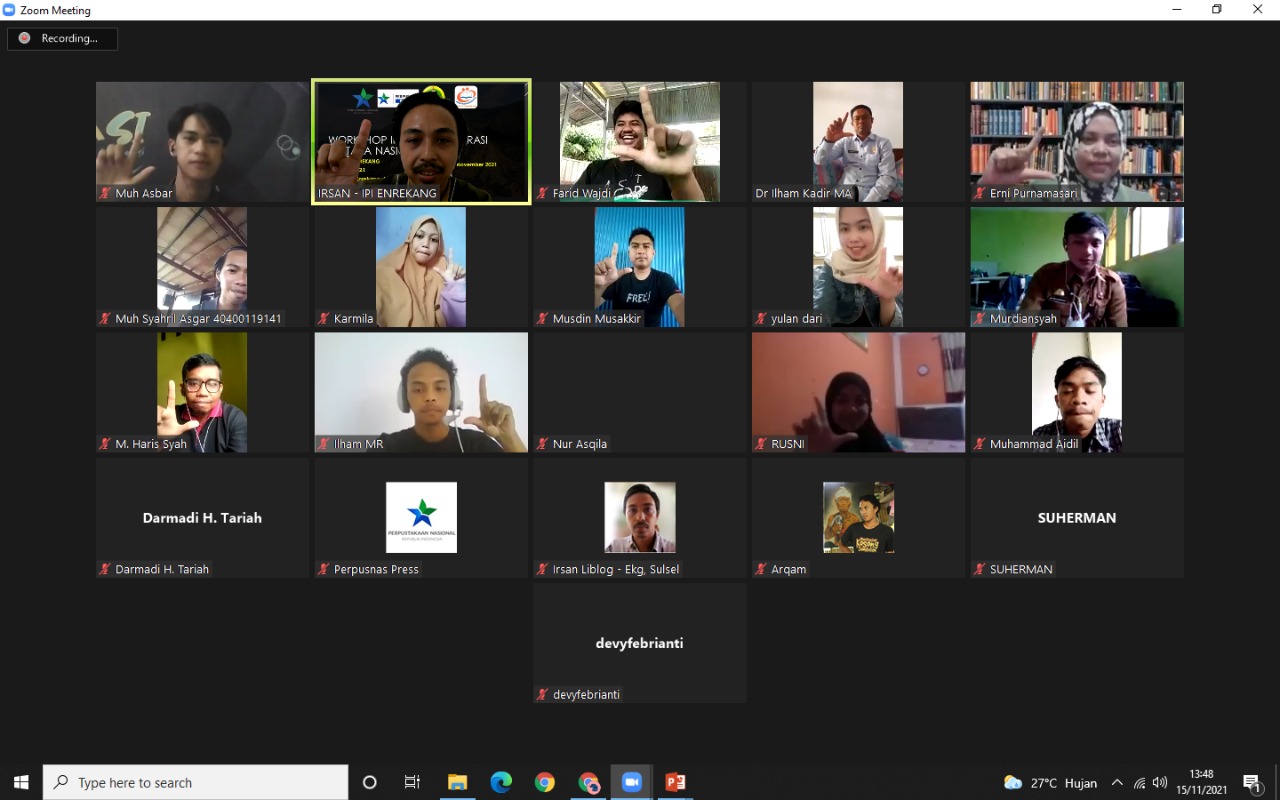








Tidak ada komentar