Suswani Ingatkan Gula, Kaunert Ingatkan Negara, Kesehatan Tak Lagi Urusan Dapur
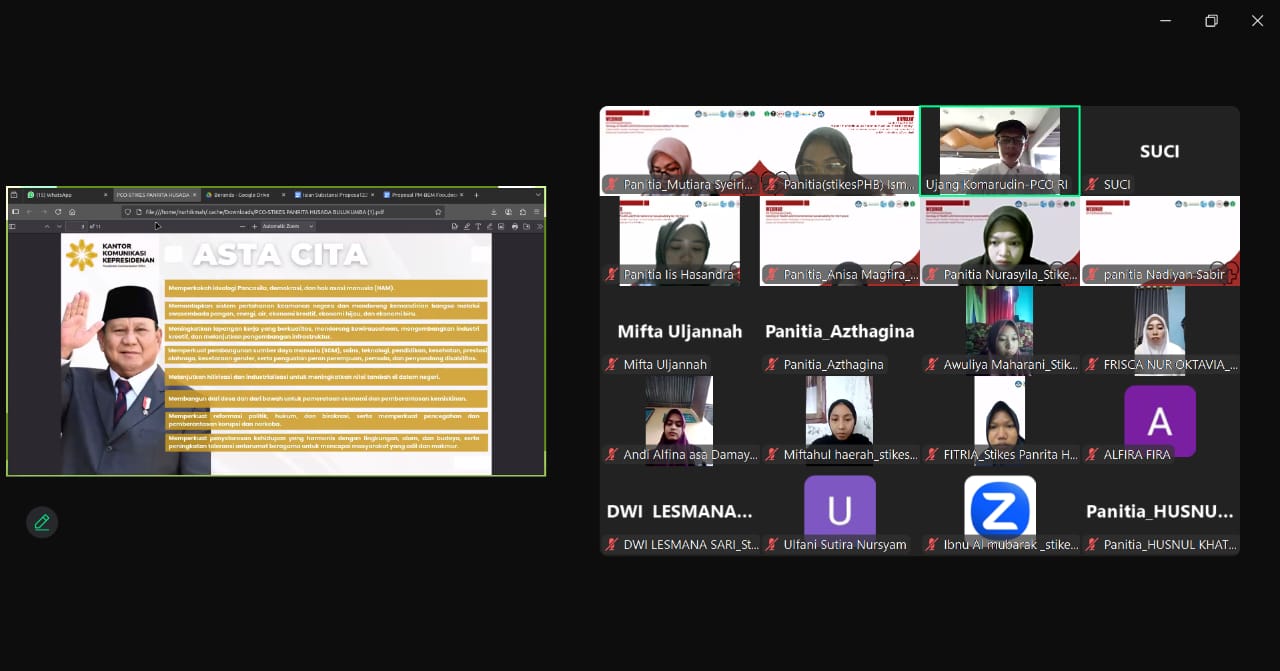
Hari kedua seminar internasional ini tak datang dengan tepuk tangan atau bunga selamat datang. Tapi ia hadir lewat data yang dingin, grafik yang tegas, dan satu benang merah: generasi muda sedang tidak baik-baik saja.
Penulis: Edy Basri
Dr. Muryati membuka pagi dengan tajuk yang sederhana: Obesitas dan Lingkungan. Tapi yang ia sampaikan jauh dari sederhana. Obesitas bukan lagi sekadar urusan timbangan dan ukuran celana. Ia kini menjadi cermin dari rusaknya gaya hidup dan lingkungan sosial.
“Lingkungan obesogenik,” katanya, sebuah istilah yang tak banyak dikenal tapi diam-diam mengintai remaja perkotaan. Ruang hijau yang menyusut, makanan cepat saji di setiap tikungan, sekolah yang lebih rajin mempromosikan nilai akademik ketimbang nilai gizi—semuanya ikut menggendutkan statistik penyakit. Di tengah gempuran konten mukbang dan kampanye ‘body positivity’ yang keliru tafsir, tubuh-tubuh muda kehilangan arah. Bukan karena lemah, tapi karena dibentuk oleh lingkungan yang tak memberi pilihan.
Lalu datanglah Dr. Andi Suswani. Ia tak perlu menakut-nakuti, karena data yang ia tampilkan sudah cukup membuat peserta Zoom menarik napas. Diabetes Mellitus pada Remaja, katanya, kini bukan kasus langka. Anak-anak sekolah sudah mulai belajar cara menyuntik insulin. Minuman manis jadi candu sosial, dan metformin—yang dulunya ampuh—kini seperti gagal paham terhadap tubuh remaja.
“Remaja kita tidak sekadar gemuk,” tegasnya. “Mereka sedang menuju kegagalan sistemik.”
Bukan hanya pankreas yang menyerah, tapi juga sistem kesehatan yang belum siap menangani usia muda sebagai pasien kronis.
Sore itu, ketika mata peserta mulai lelah, datanglah suara dari Fatoni University, Thailand. Prof. Dr. Muh. Shakree Manyunuh bukan hanya datang dengan ilmu, tapi juga iman. Ia bicara tentang kesaksamaan kesihatan, kesetaraan dalam pelayanan, dan kebijakan kesehatan yang bersandar pada maqasid syariah.
“Kesehatan bukan hanya hak, tapi amanah,” ucapnya. Sebuah frasa yang menggema dalam ruang sunyi digital. Ia tak menyebut nama-nama politisi, tapi kalimatnya terasa seperti nasihat untuk mereka yang kini memegang kuasa: Janganlah engkau membangun rumah sakit megah, jika masyarakat masih tak mampu menjangkaunya.
Beralih ke Indonesia, Dr. Ujang Kamaruddin hadir dengan semangat ASTA CITA. Delapan janji pembangunan sumber daya manusia yang disampaikan Prabowo-Gibran bukan sekadar jargon kampanye. Di tangan Ujang, ASTA CITA menjadi lembar kerja nasional: beasiswa, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kurikulum riset, hingga layanan kesehatan gratis yang merata.
Ia tidak sedang berorasi politik. Tapi apa yang ia sampaikan jelas: kalau SDM adalah fondasi bangsa, maka perhatian pada pendidikan dan kesehatan bukan pilihan, tapi keharusan.
“Tak ada generasi emas tanpa perut kenyang dan pikiran yang sehat,” katanya.
Dan akhirnya, dari ujung barat Eropa, datang suara Prof. Dr. Cristian Kaunert dari University of South Wales, Inggris. Judul materinya lugas dan global: Why Is Health as Security Issue. Tapi isinya justru sangat lokal.
Ia mengingatkan, betapa sistem kesehatan bisa menjadi titik lemah sebuah negara. Pandemi COVID-19 jadi bukti: ketika masker jadi rebutan, dan ICU jadi ruang rebutan, maka kesehatan sudah menjelma isu keamanan nasional. Bahkan militer pun bisa lumpuh karena demam berdarah.
“Kesehatan tak bisa lagi dipisahkan dari politik, ekonomi, bahkan pertahanan,” ucapnya.
Dari pembicaraan hari ini, kita belajar bahwa penyakit bukan cuma urusan tubuh. Ia bersinggungan dengan kebijakan, keadilan, bahkan peradaban. Dari obesitas hingga diabetes, dari prinsip Islam hingga ancaman keamanan global—semuanya kembali ke satu titik: manusia dan kemampuannya menjaga amanah bernama kesehatan.
Dan seperti kemarin, seminar ini tetap berlangsung dari dua kampus yang jauh dari sorotan pusat: STIKES Panrita Husada Bulukumba dan IAI Rawa Aopa Konawe Selatan. Tapi lagi-lagi, mereka berhasil menjahit percakapan dunia dari sebuah pojok timur Indonesia.
Zoom masih terbuka. Diskusi terus mengalir. Dan hari esok sudah dijanjikan lebih padat.
Karena ilmu tak mengenal batas. Dan karena di ujung sinyal yang kadang putus, kampus kecil ini sedang menyambung dunia. (*)
Penulis (edybasri) adalah seorang jurnalis, sekaligus akademisi hukum di Bumi Nene Mallomo-Sidrap, Sulsel.



















Tidak ada komentar