Soal Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah?

Jakarta, katasulsel.com — Ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka forum di hadapan para surveyor, ia tak sekadar bicara teknis pertanahan. Ia menggedor logika usang yang masih bergentayangan di kepala sebagian pemilik tanah: bahwa sertifikat tanah adalah warisan yang sakral, tak boleh diganggu gugat, meski hanya dijadikan kandang ilalang bertahun-tahun.
“Tanah itu nggak ada yang punya. Yang punya ya negara. Orang itu hanya diberi hak. Tapi ini tanah mbah saya, katanya. Lah saya mau tanya, emang mbahmu bisa bikin tanah?” ujar Nusron, dalam nada yang bukan cuma retoris, tapi juga menyengat urat warisan feodal yang kadung dianggap suci.
Pernyataan ini mengiringi langkah tegas Kementerian ATR/BPN untuk menarik kembali tanah-tanah yang menganggur selama dua tahun. Tak main-main, hingga Agustus ini, sebanyak 100 ribu hektare tanah dalam status ‘dibuntuti negara’ alias sedang dipantau. Status resminya: tanah terlantar. Prosedurnya? Tentu tidak seperti rebutan petak sawah antar keluarga. Negara menghitungnya matang, memerlukan 578 hari untuk mengkaji, menyurati, dan akhirnya mencabut hak atas lahan yang dianggap mangkrak tanpa kontribusi.
“Kalau sudah dua tahun nggak diapa-apain, itu bukan tanah mati, itu pemiliknya yang ‘mati gaya’. Negara butuh lahan produktif, bukan lahan nostalgia,” lanjut Nusron, menyentil fenomena umum di mana pemilik tanah lebih sibuk memelihara cerita warisan ketimbang memikirkan kegunaannya di tengah krisis lahan.
Pernyataan Nusron tak pelak memantik reaksi, sebagian bertepuk tangan, sebagian lain mencibir: katanya negara seenaknya mengganggu hak milik rakyat. Tapi di balik satire tajam sang menteri, terselip satu pesan: tanah adalah sumber daya terbatas, bukan album kenangan.
“Yang namanya hak itu melekat selama digunakan. Kalau tidak, ya dikembalikan. Sama kayak SIM. Coba simpan SIM tapi nggak pernah nyetir selama dua tahun, terus bikin pelanggaran. Apa polisi tinggal diam?” ucap seorang pegawai ATR/BPN dengan senyum setengah geli.
Bagi yang masih menyimpan tanah sekadar jadi penanda silsilah keluarga, sebaiknya mulai berpikir ulang. Negara tak sedang menyita, melainkan menyelamatkan tanah dari menjadi situs arkeologi keluarga. Di zaman di mana lahan kian sempit dan kebutuhan rakyat makin meluas, tanah bukan lagi soal ‘punya siapa’, tapi ‘dimanfaatkan untuk apa’.
Lalu bagaimana jika tanah itu masih dalam proses izin usaha atau sedang menunggu rencana besar? Pemerintah menjawab, akan selektif. Tapi yang sekadar menanam kenangan tanpa niat panen, siap-siap dicabut haknya.
Karena negara ini tak dibangun di atas nostalgia, melainkan kebutuhan yang terus bergerak. Dan tanah, sebagaimana harapan rakyat, tak bisa selamanya jadi benda mati.(*)
Editor: Tipoe Sultan/Reporter:Achmad/Jakarta
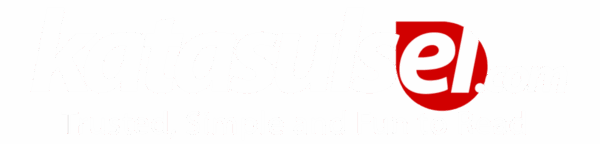


















Tidak ada komentar