 Wahyuddin Halim
Wahyuddin HalimWahyuddin Halim
(warga kampus sejak 1988)
Terinspirasi dari buku Dark Academia: How Universities Die (London: Pluto Press, 2021) karya Peter Fleming, saya merenung panjang tentang apa yg sebenarnya sedang terjadi di dunia kampus hari ini, baik di Barat maupun di Indonesia.
Buku tersebut bukan sekadar kritik terhadap gejala neoliberalisme dalam pendidikan tinggi. Ia adalah semacam otopsi intelektual atas kematian perlahan sebuah institusi yang dulu sangat kita percaya, universitas. Walau terbit lima tahun lalu, apa yg Fleming ulas justru terasa semakin relevan sekarang. (Tentu saja, ini belum menyentuh persoalan “ijazah palsu” yg tetap bertengger di puncak tangga lagu-lagu kampus terpopuler di negeri ini, hehe.)
Dulu, banyak orang menganggap bekerja di kampus sebagai pekerjaan ideal, penuh otonomi, kedalaman intelektual, dan relasi yg hangat. Ada pula kepuasan batin karena menyentuh kehidupan orang lain melalui ilmu. Tetapi sekarang, coba tanyakan kpd para dosen muda, mahasiswa pascasarjana, atau staf kontrak di universitas, apa yg mereka rasakan?
Dalam Dark Academia, Fleming menyebut ini sebagai “kematian perlahan” universitas. Bukan karena gedungnya runtuh, tetapi karena jiwanya direnggut. Universitas kini dikelola seperti korporasi. Yg dihitung bukanlah pencapaian intelektual, melainkan angka-angka akreditasi. Yg dikejar bukanlah makna, tetapi skor dan pujian dari sistem perangkingan eksternal. Para dosen didorong untuk menulis cepat dan sebanyak mungkin demi akumulasi angka kredit. Mahasiswa dibentuk agar “siap kerja”, bukan siap berpikir, apalagi siap hidup secara mandiri.
Di Indonesia, gejala ini semakin nyata. Banyak program studi disesuaikan bukan dengan kebutuhan masyarakat untuk belajar berpikir kritis dan reflektif, melainkan dengan tuntutan pasar yg cepat berubah. Mata kuliah yg dianggap tidak menghasilkan langsung dihapus. Bidang humaniora diringkas, sejarah dipangkas, dan filsafat ditebas. Padahal justru di situlah tempat pertanyaan-pertanyaan besar ttg kehidupan dan dunia diajarkan, ttg tujuan, makna, dan cara hidup yg sejati.
Sementara itu, beban kerja dosen semakin berat. Target publikasi terus bertambah. Tugas-tugas administratif menggunung, mulai dari Beban Kerja Dosen (BKD), Evaluasi Laporan Kinerja Dosen (ELKD), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), hingga berbagai platform seperti SISTER dan SINTA. Namun ruang untuk membaca, meneliti, dan berpikir justru semakin menyempit.
Tidak sedikit yg menjalani kehidupan akademik dalam keheningan, terjebak rutinitas teknis, dan perlahan kehilangan cinta terhadap jalan intelektual yg dulu mereka pilih. Tidak jarang pula yg menyambi pekerjaan lain secara penuh waktu (full time) dan mengajar hanya sambilan (part time). Syukur-syukur jika dapat tambahan tugas struktural, alias menjadi pejabat kampus.
Mahasiswa pun tak luput dari tekanan. Mereka masuk kampus dengan harapan akan masa depan yg cerah. Namun, seiring waktu, mereka segera berhadapan dengan banyak hal yg melelahkan dan membosankan. Setiap hari dicekoki ceramah ttg hal-hal yg tidak relevan dengan topik perkuliahan. Tugas menulis makalah yg pada akhirnya menjadi artikel jurnal atas nama dosen mereka. Presentasi dari PowerPoint, entah buatan Canva atau SlideMaker, hampir setiap pertemuan, sementara dosennya lebih banyak berperan sebagai moderator pasif.
Belum lagi berbagai bentuk pungutan berkedok institusional, biaya pendaftaran ujian jalur mandiri, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), ramah tamah wisudawan, biaya wisuda, hingga surat bebas pustaka.
Tetapi setelah empat tahun kuliah, atau bahkan lebih cepat, tidak jarang mereka lulus ke dunia yg tidak pasti, dunia yg sangat kompetitif secara algoritmik dan harus bersaing dengan ribuan lainnya yg membawa ijazah serupa. Banyak di antara mereka memiliki transkrip dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,90 dan predikat Cum Laude. Namun tetap saja, mereka bertanya dalam hati, kuliah selama ini untuk apa?
Di tengah semua itu, tentu masih ada ruang-ruang kecil yg tetap menyala. Kelas-kelas kecil yg jujur, hangat & tulus. Dosen-dosen yg mengajar dengan sepenuh hati, bukan sekadar memenuhi beban kredit. Dalam pengalaman saya mengajar hampir tiga dekade, selalu ada mahasiswa yg datang bukan hanya mengejar nilai, melainkan sungguh ingin memahami, ingin menjadi.
Dan mereka inilah yg sering menyapa saya, bertahun-tahun kemudian, lewat surat elektronik atau media sosial dari Mesir, Iran, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Eropa, dan tempat-tempat lain yg jauh dari almamater mereka. Mereka mengirimkan foto kehidupan mereka di almamater yg baru, yang begitu jauh dalam hal jarak, kualitas, integritas, dan spiritualitas, dibanding almamater mereka sebelumnya..hehe.
Mereka tidak lupa berterima kasih atas surat rekomendasi yg saya berikan. Padahal jelas, yg lebih menentukan adalah kecerdasan dan tekad mereka sendiri. Mereka yg sejak awal memilih menetapkan target pribadi yg lebih tinggi daripada sekadar IPK dan predikat kelulusan. Mereka yg diam-diam menjadi kutu buku di sudut perpustakaan kampus, alih-alih mengutuk & meratapi sistem yg menjadikan universitas sebagai pabrik sarjana.
Mahasiswa seperti inilah, satu dari seratus atau dua ratus barangkali, yg masih menjadi denyut nyawa terakhir universitas. Pada merekalah harapan itu masih menyala. Dari mereka kita bisa membayangkan kemungkinan kebangkitan kembali semangat intelektualisme dan tradisi akademik Indonesia.
Peter Fleming mengingatkan, jika kita tidak bertindak sekarang, universitas akan kehilangan seluruh fondasinya. Bukan hanya kehilangan makna, tetapi kehilangan raison d’être, elan vital, alasan keberadaannya. Kita akan memiliki gedung-gedung besar, luas, dan mewah, serta sistem digital yg supercanggih, tetapi kita kehilangan keberanian berpikir. Kehilangan kejujuran akademik, plagiarisme menjadi hal lumrah, menjadi budaya akademik. Kampus kehilangan kemandirian. Segala hal diatur dari kementerian. Dan tentu saja, kehilangan harga diri. Mate Siri’, kata orang Bugis-Makassar-Mandar.
Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus ikut arus sistem ini, atau menjaga bara kecil yg tersisa itu? Apakah kita masih percaya bahwa kampus adalah ruang merdeka untuk berpikir dan berkreasi, atau cukup puas menjadikannya pabrik gelar? atau pabrik.. hehe.
Mungkin waktunya sudah mendesak. Tapi selama masih ada yang terus membaca, menulis, bertanya, dan mendengar, maka harapan itu belum padam. Maka, jgn berhenti bertanya! Jangan berhenti menulis!
Kita, “MASIH BISA”. (*)
Editor: Edy Basri




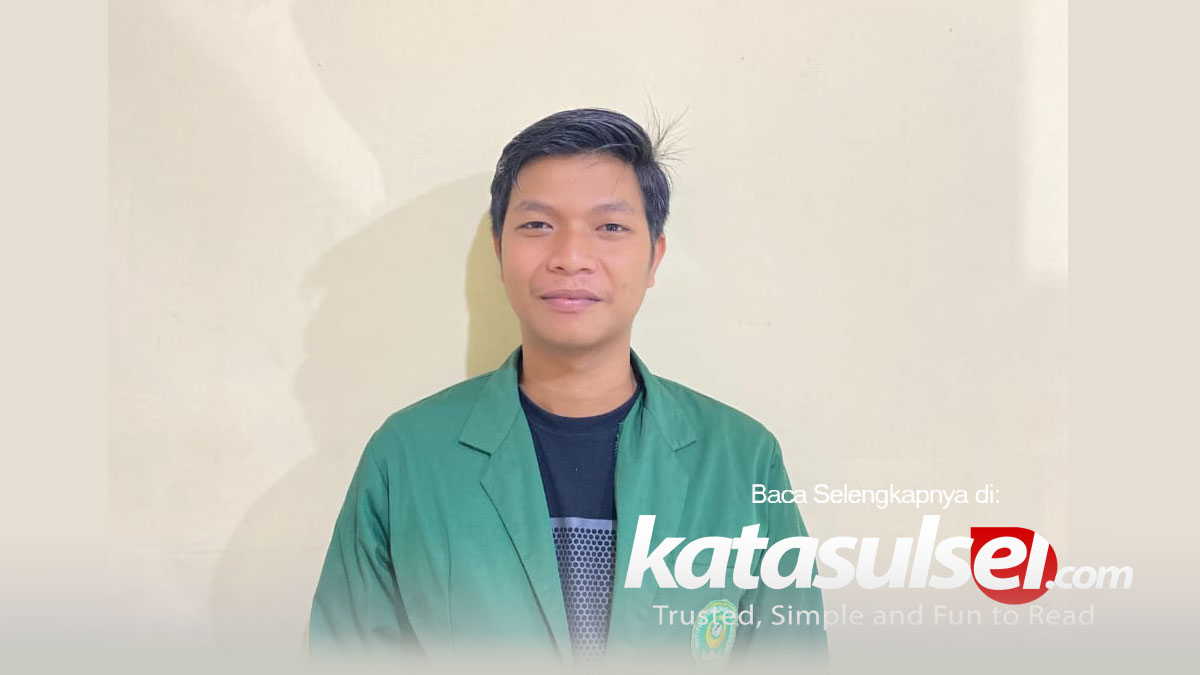











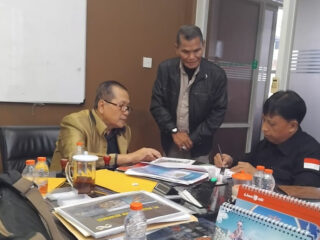


Tidak ada komentar