📣 Ikuti saluran resmi WhatsApp kami sebelum membaca berita!
Join WhatsAppOleh: Chayrasafana Nur Amni
Perkembangan media sosial telah mengubah cara remaja membangun relasi, mengekspresikan diri, hingga menilai keberhargaan personal. Jika sebelumnya ruang sosial dibatasi oleh lingkungan sekolah dan keluarga, kini dunia digital menghadirkan panggung tanpa batas, tempat remaja dapat dilihat, dinilai, dan dibandingkan setiap saat. Dalam konteks inilah media sosial tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkan menjadi arena pembentukan identitas yang sarat tekanan psikologis.
Bagi remaja, fase pencarian jati diri adalah proses yang kompleks. Media sosial menawarkan ilusi kemudahan: cukup dengan unggahan foto, video singkat, atau status, seseorang bisa memperoleh pengakuan dalam bentuk likes, komentar, dan jumlah pengikut. Namun, pengakuan digital ini sering kali bersifat semu. Ketika validasi menjadi tolok ukur nilai diri, remaja berisiko terjebak dalam siklus perbandingan sosial yang melelahkan secara mental.
Arus konten yang tak pernah berhenti membuat remaja terus-menerus terpapar pencapaian orang lain, standar kecantikan tertentu, gaya hidup ideal, hingga narasi kesuksesan instan. Tanpa disadari, media sosial menciptakan ruang kompetisi yang tidak seimbang: yang ditampilkan adalah potongan terbaik dari kehidupan seseorang, sementara proses, kegagalan, dan realitas di balik layar kerap disembunyikan. Akibatnya, banyak remaja merasa tertinggal, kurang berharga, atau tidak cukup baik, meskipun kenyataannya setiap individu memiliki lintasan hidup yang berbeda.
Sejumlah kajian psikologi sosial menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial berkorelasi dengan meningkatnya kecemasan, gangguan konsentrasi, dan kelelahan emosional pada remaja. Aktivitas membandingkan diri serta ketergantungan pada respons digital terbukti dapat menurunkan kesejahteraan psikologis. Media sosial, dalam konteks ini, berfungsi sebagai penguat emosi—baik positif maupun negatif—tergantung pada konten yang dikonsumsi dan kondisi psikologis penggunanya.
Persoalan ini diperparah oleh mekanisme algoritma platform digital yang cenderung menampilkan konten serupa dengan apa yang sebelumnya diakses. Ketika seorang remaja sedang berada dalam kondisi emosional tertentu, misalnya sedih atau cemas, algoritma justru memperkuat suasana tersebut dengan menghadirkan konten sejenis. Alih-alih menjadi ruang pelepas stres, media sosial dapat berubah menjadi ruang gema emosional yang memperdalam tekanan mental.
Kemunculan teknologi kecerdasan buatan juga menambah kompleksitas persoalan. Konten digital kini semakin sulit dibedakan antara fakta dan manipulasi. Visual yang tampak realistis, narasi yang persuasif, serta informasi yang viral dalam waktu singkat membuat remaja rentan terpengaruh apabila tidak dibekali kemampuan literasi digital yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi cara berpikir, regulasi emosi, dan kepercayaan diri generasi muda.
Data mengenai kesehatan mental remaja di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tekanan digital—mulai dari perbandingan sosial, cyberbullying, hingga kecanduan notifikasi—menjadi faktor signifikan yang memperkuat risiko gangguan psikologis. Ketika media sosial dijadikan satu-satunya ruang aktualisasi diri tanpa dukungan keluarga dan lingkungan, remaja berada dalam posisi yang semakin rentan.
Namun, menempatkan media sosial semata-mata sebagai penyebab masalah juga tidak sepenuhnya adil. Media sosial tetap memiliki potensi positif sebagai ruang ekspresi, edukasi, dan penguatan jejaring sosial, asalkan digunakan secara sadar dan terkontrol. Tantangannya terletak pada bagaimana membekali remaja dengan kemampuan memilah informasi, mengelola emosi, serta memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh metrik digital.
Upaya kolektif menjadi kunci. Sekolah perlu memperkuat layanan konseling dan pendidikan kesehatan mental. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi terbuka dan mendampingi penggunaan gawai. Sementara itu, negara dan pemangku kepentingan harus mendorong literasi digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukanlah apakah media sosial berbahaya atau tidak, melainkan sejauh mana kita—sebagai masyarakat—siap membimbing remaja agar mampu menempatkan media sosial sebagai alat, bukan penentu jati diri. Tanpa kesadaran dan pendampingan yang berkelanjutan, ruang ekspresi itu dapat berubah menjadi sumber tekanan mental yang sunyi namun nyata. (*)

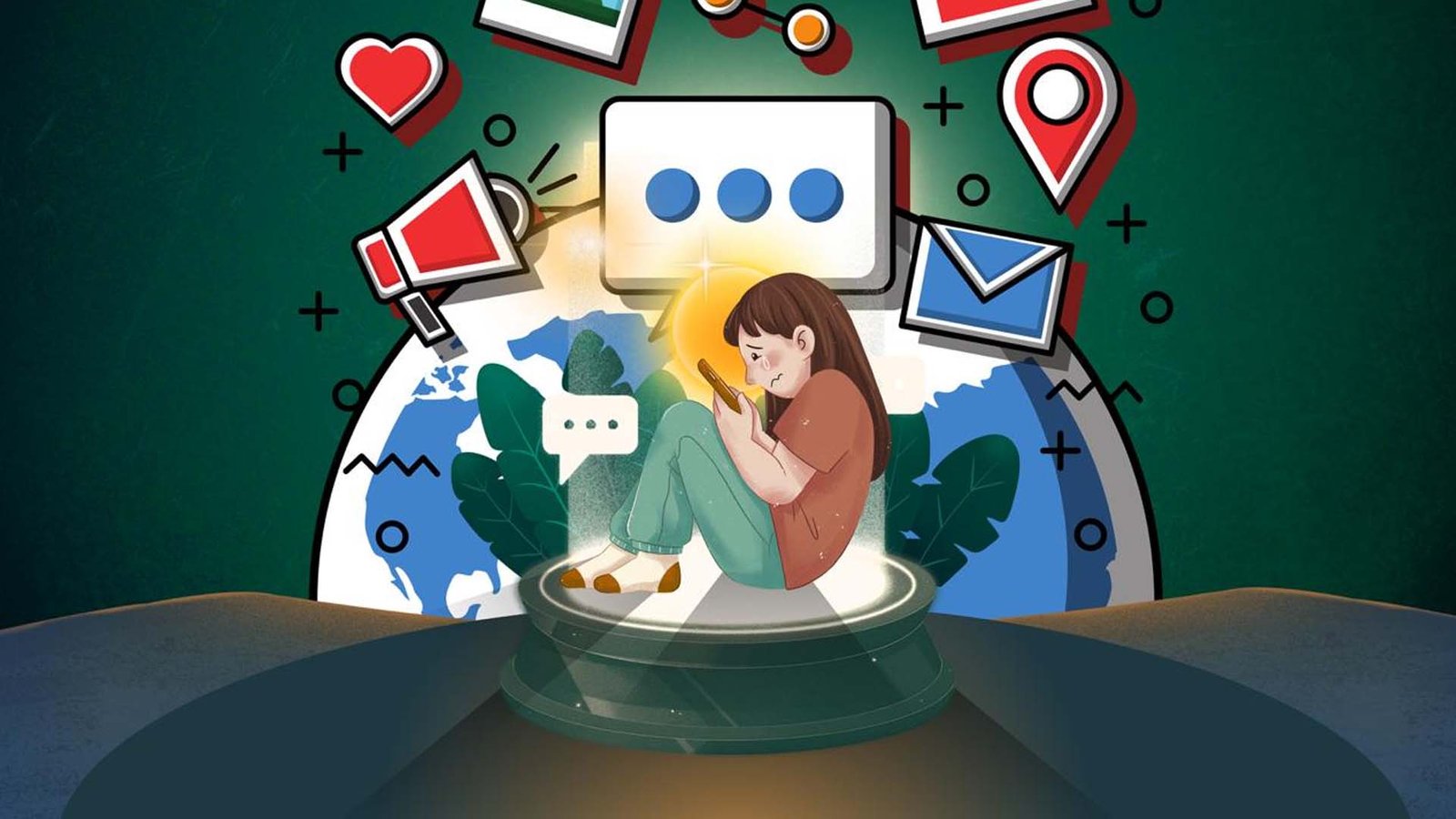


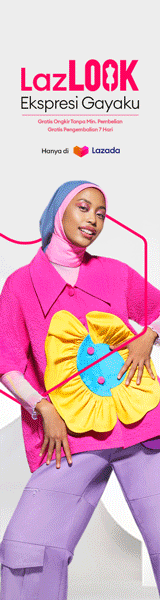










Tinggalkan Balasan