📣 Ikuti saluran resmi WhatsApp kami sebelum membaca berita!
Join WhatsAppOrang Wajo itu, sejak dulu hidup dengan air.

Oleh: Edy Basri
BUKAN sekadar hidup di dekat sungai, tapi hidup bersama sungai. Sungai bukan latar belakang. Sungai adalah urat nadi. Jalur ekonomi. Jalan raya paling awal sebelum aspal dikenal.
Salah satunya Sungai Walanae.
Sungai ini mengalir panjang, melintasi sejarah Wajo yang tidak pernah sepenuhnya tenang. Dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga republik. Dari perahu kayu sampai jembatan gantung.
Walanae tidak pernah berhenti. Ia mengalir pelan, tapi konsisten. Sama seperti karakter orang Wajo: tidak banyak bicara, tapi keras bertahan.
Di atas sungai itulah jembatan gantung di Kecamatan Tempe berdiri. Menghubungkan Tokampu di Kelurahan Siengkang dengan Tonronge di Wiringpalenae. Sebuah bentangan sederhana. Tidak megah. Tidak monumental. Tapi vital.
Seperti kebanyakan infrastruktur di daerah, jembatan itu lahir bukan dari proyek besar. Ia lahir dari kebutuhan. Dari jarak yang terlalu jauh jika harus memutar. Dari keinginan sederhana: cepat sampai.
Dulu, sebelum jembatan itu ada, orang menyeberang dengan perahu kecil. Mengandalkan arus. Menghafal musim. Menunggu air surut. Tidak semua berani.
Ketika jembatan gantung dibangun, ia mengubah banyak hal. Anak sekolah tidak lagi terlambat karena sungai pasang. Petani tidak harus memutar berjam-jam. Aktivitas ekonomi menjadi lebih hidup.
Jembatan itu menjadi simbol kecil dari kemajuan.
Tapi seperti sungainya, waktu tidak pernah berhenti bekerja.
Air Walanae bukan air yang jinak. Ia membawa endapan. Ia menggerus tepi. Ia menggeser tanah sedikit demi sedikit. Tidak terasa. Tapi pasti.
Yang pertama menyerah bukan lantai jembatan. Bukan tali baja. Melainkan pondasi di tepi sungai. Bagian yang tidak terlihat. Yang jarang diperhatikan. Tapi justru paling menentukan.
Ketika pondasi mulai bergeser, jembatan sebenarnya sudah memberi tanda. Goyangan kecil. Getaran yang terasa di telapak kaki. Tapi tanda-tanda seperti ini sering kalah oleh rutinitas.
Sampai kekhawatiran itu akhirnya sampai ke ruang parlemen.
Di DPRD Kabupaten Wajo, ada dua orang yang wilayah pemilihannya tepat di sana: Taqwa Gaffar dan Andi Bayuni Marzuki. Keduanya memahami satu hal penting: di Wajo, urusan sungai bukan urusan sepele.
Sejarah Wajo mencatat, konflik dan kemajuan sering kali bermula dari air. Dari sawah yang kekeringan. Dari sungai yang meluap. Dari irigasi yang macet.
Karena itu, kerusakan di tepi Walanae bukan sekadar masalah teknis. Ia adalah ancaman terhadap ritme hidup masyarakat.
Mereka tidak memilih jalan populer.
Tidak ada foto berdiri di tengah jembatan. Tidak ada video berlatar musik sedih. Tidak ada narasi heroik.
Mereka memilih jalan birokrasi—jalan yang sering dianggap tidak menarik, tapi justru menentukan.
Langkah pertama: Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan–Jeneberang di Makassar.
Dalam sistem negara, sungai besar seperti Walanae bukan urusan kabupaten. Ia berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS. Di sanalah urusan konservasi, pengendalian daya rusak air, dan perlindungan tebing sungai diputuskan.
“Kalau rusaknya di tepi sungai, itu kewenangan BBWS,” kata Taqwa Gaffar.
Kalimat itu terdengar administratif. Tapi sesungguhnya itulah inti dari kerja parlemen: menempatkan masalah di meja yang tepat.
Mereka diterima Kepala Bidang PJTA BBWS, Hayatuddin Tuasikal. Pembicaraan tidak berputar pada siapa yang paling berjasa. Tapi pada apa yang harus dilakukan.
Peta dibuka. Titik kerusakan ditandai. Aliran Walanae dianalisis. Karena sungai tidak bisa diselesaikan dengan janji. Ia hanya bisa ditangani dengan perhitungan.
BBWS merespons. Tim teknis akan turun. Penanganan akan disiapkan.
Namun jembatan tidak hanya berdiri di atas sungai. Ia juga berdiri di atas jaringan jalan.
Maka langkah berikutnya adalah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Sulawesi Selatan. Urusan atas jembatan, struktur, dan konektivitas.
Komisi III DPRD Wajo akan membawa usulan resmi. Lengkap. Terukur. Dengan dasar kebutuhan masyarakat.
Bahkan mereka berencana menemui Andi Iwan Aras, mencari penguatan di tingkat pusat. Bukan untuk sensasi politik, tapi untuk memastikan jembatan kecil di Tempe tidak kalah oleh proyek besar di kota.
Beginilah kerja wakil rakyat di daerah seperti Wajo.
Tidak spektakuler. Tidak viral. Tapi berlapis. Pelan. Dan sering kali melelahkan.
Di luar sana, Sungai Walanae tetap mengalir. Tidak peduli siapa bupatinya. Tidak peduli siapa anggota dewan. Ia hanya menjalankan kodratnya.
Jembatan itu masih berdiri. Masih dilalui. Masih menjadi penghubung kehidupan.
Masyarakat mungkin tidak tahu detail prosesnya. Mereka tidak perlu tahu istilah BBWS, BPJN, atau Direktorat Jenderal.
Mereka hanya ingin satu hal: jembatan itu aman.
Dan di situlah politik seharusnya bekerja. Bukan sebagai panggung. Tapi sebagai penghubung. Seperti jembatan itu sendiri.
Di Wajo, sejarah mengajarkan satu hal: siapa yang mengabaikan air, akan ditinggalkan oleh zaman.
Karena sungai boleh sunyi. Tapi dampaknya selalu panjang. (*)




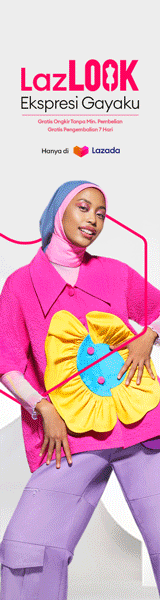










Tinggalkan Balasan