MAKASSAR – Ia bukan hanya jurnalis. Edy Basri juga seorang akademisi Ilmu Hukum. Itulah yang membuat pandangannya tentang posisi Polri terasa berbeda: lebih tenang, lebih konseptual, dan berangkat dari logika negara hukum.
Menjelang pelantikannya sebagai Ketua Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulawesi Selatan pada 14 Februari 2026 (Usai kantongi SK, red), Edy memilih menyampaikan satu sikap yang kerap memantik perdebatan nasional: Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Bagi Edy, ini bukan soal suka atau tidak suka pada institusi. Ini soal arsitektur konstitusional.
“Dalam perspektif ilmu hukum tata negara, Polri adalah organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan,” ujar Edy.
Logikanya sederhana, tapi sering diabaikan. Jika Polri ditarik ke bawah kementerian, maka akan terjadi distorsi kewenangan. Presiden, kata Edy, justru akan kehilangan kendali langsung terhadap instrumen penting negara.
“Padahal, Presiden bertanggung jawab langsung atas keamanan nasional,” katanya.
Sebagai akademisi hukum, Edy menilai penempatan Polri di bawah Presiden memberi kepastian hukum sekaligus kejelasan komando. Tidak ada ruang abu-abu. Tidak ada tafsir ganda soal siapa yang memegang kendali akhir.
Di sinilah ia berbeda dari sekadar wacana politik.
“Ini bukan isu politik kekuasaan. Ini isu desain negara,” tegasnya.
Edy mengingatkan, dalam teori trias politica modern, institusi seperti Polri memang tidak ditempatkan di bawah kekuasaan legislatif maupun kementerian teknis. Ia berdiri sebagai alat negara yang harus netral, profesional, dan langsung bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan.
“Kalau Polri di bawah kementerian, maka ada risiko subordinasi sektoral. Itu bertentangan dengan prinsip independensi penegakan hukum,” ujarnya.
Pandangan itu ia tarik ke konteks nasional hari ini. Tantangan keamanan bukan lagi soal kriminalitas konvensional. Ada kejahatan siber, konflik sosial, hingga isu keamanan berbasis informasi.
“Respons negara harus cepat. Jalur komando yang pendek adalah kunci,” katanya.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, Edy melihat langsung bagaimana Polda Sulsel bekerja di wilayah dengan karakter sosial yang kuat, emosional, dan sangat menjunjung nilai lokal. Menurutnya, kepolisian di daerah seperti Sulsel membutuhkan legitimasi kuat dari pusat agar bisa bertindak tegas sekaligus adil.
“Polisi di daerah tidak boleh ragu-ragu karena bingung soal struktur,” ujarnya.
Lebih dekat lagi, Sidrap menjadi contoh menarik. Di wilayah agraris dengan relasi sosial yang erat, Polres Sidrap sering kali berperan bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator sosial.
“Di daerah seperti Sidrap, polisi itu bukan sekadar aparat. Ia hadir di ruang sosial masyarakat dan itu sudah berkali-kali sukses dilakukan di bawah komando Kapolres AKBP Dr. Fantry Taherong,” kata Edy.
Model kerja seperti itu, menurutnya, hanya mungkin jika Polri memiliki otoritas yang jelas dan tidak terfragmentasi oleh kepentingan kementerian.
Sebagai jurnalis berlisensi wartawan utama Dewan Pers sejak 2019, Edy menekankan satu hal penting: dukungan terhadap struktur Polri di bawah Presiden tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran tanpa kritik.
“Justru karena Polri langsung di bawah Presiden, pengawasan publik harus lebih kuat,” ujarnya.
Di situlah peran pers dan masyarakat sipil menjadi krusial.
Menjelang pelantikannya sebagai Ketua KJI Sulsel, Edy Basri seakan ingin menegaskan identitasnya: jurnalis yang berpikir sebagai akademisi, dan akademisi yang tetap berpihak pada kepentingan publik.
Baginya, negara hukum bukan sekadar pasal dan undang-undang. Ia hidup dalam desain kelembagaan yang tepat.
Dan dalam desain itu, menurut Edy, Polri memang seharusnya tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. (*)






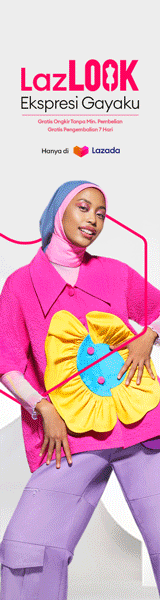










Tinggalkan Balasan