📣 Ikuti saluran resmi WhatsApp kami sebelum membaca berita!
Join WhatsAppKatasulsel.com — Pagi itu, Rabu 28 Januari 2026, ruang kerja lantai III Kantor Bupati Sidenreng Rappang tampak seperti biasa. Tidak ada protokol yang lalu-lalang. Tidak ada rombongan tamu. Tidak ada kamera televisi. Yang ada hanya seorang bupati duduk menghadap layar, berbicara pelan, sesekali mencatat, sesekali mengangguk.
Ia bukan sedang rapat pemerintahan. Bukan pula menerima laporan proyek. Ia sedang diuji.
Nama di layar itu Syaharuddin Alrif. Jabatan di pundaknya bupati. Tapi pagi itu, statusnya mahasiswa doktoral. Program S3 Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Ilmu Pertanian.
Ada kepala daerah yang berhenti belajar begitu dilantik. Ada pula yang baru benar-benar belajar setelah memegang kekuasaan. Syaharuddin termasuk yang kedua.
Judul yang ia ajukan panjang. Sangat panjang. Tidak ramah clickbait. Bahkan terkesan “terlalu akademik” untuk seorang bupati aktif. Model Strategi Kebijakan Agribisnis Tanaman Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Porang.
Tanaman yang dulu dianggap liar. Tumbuh di sela-sela kebun. Tidak diperhitungkan. Kini menjadi kata kunci. Menjadi bahan seminar doktoral. Menjadi arah kebijakan.
Dan di situlah letak ceritanya.
Syaharuddin tidak jatuh cinta pada porang karena tren. Ia tidak tiba-tiba mengangkat porang karena harga sedang naik. Ia melihat porang sebagai gejala. Sebagai peluang. Sebagai pintu masuk untuk membicarakan sesuatu yang lebih besar: bagaimana kebijakan daerah seharusnya bekerja.
Banyak kepala daerah berbicara tentang kesejahteraan petani. Tidak semuanya paham mekanismenya. Syaharuddin memilih jalan yang tidak populer: ia memasukinya lewat riset.
Ia tahu, kebijakan tanpa basis ilmiah hanya akan jadi slogan. Dan slogan, betapapun lantangnya, tidak pernah cukup untuk mengubah nasib petani.
Di layar Zoom itu, para profesor Unhas mendengarkan. Mereka bukan bawahan. Mereka penguji. Mereka bebas mengkritik. Bebas mematahkan argumen. Bebas bertanya dengan nada akademik yang dingin.
Dan Syaharuddin menerimanya.
Ia tidak berbicara sebagai pejabat yang ingin dibenarkan. Ia berbicara sebagai peneliti yang ingin diuji.
Di situlah bedanya.
Porang dalam disertasinya tidak diposisikan sebagai komoditas ajaib. Ia tidak menjanjikan surga instan. Ia justru berhati-hati. Ia bicara tentang risiko. Tentang keberlanjutan. Tentang bahaya euforia komoditas.
Sidrap, baginya, tidak boleh mengulang cerita lama. Tanam ramai-ramai. Panen ramai-ramai. Lalu jatuh bersama-sama.
Karena itu ia bicara model. Bukan proyek. Bicara strategi. Bukan sekadar program tahunan.
Ia mengaitkan porang dengan kebijakan agribisnis. Dengan peran pemerintah daerah. Dengan kepastian pasar. Dengan perlindungan petani. Dengan lingkungan.
Kalimat-kalimatnya tidak meledak-ledak. Tapi tertata. Terstruktur. Terlihat bahwa ini bukan bahan pidato. Ini hasil perenungan panjang.
Menariknya, semua itu dilakukan dari ruang kerja bupati.
Meja yang sama tempat ia menandatangani surat keputusan. Kursi yang sama tempat ia menerima laporan OPD. Ruangan yang sama tempat ia memimpin Sidrap.
Hari itu, ruang kekuasaan berubah menjadi ruang ilmu.
Ini bukan kebetulan. Ini pilihan sadar.
Syaharuddin seolah ingin menunjukkan bahwa jabatan tidak boleh mematikan rasa ingin tahu. Bahwa kekuasaan seharusnya memperbesar tanggung jawab intelektual, bukan malah menumpulkannya.
Banyak pejabat mengejar gelar untuk prestise. Untuk tambahan gelar di kartu nama. Untuk foto wisuda. Syaharuddin justru sebaliknya. Ia mengambil gelar untuk memikul beban yang lebih berat.
Bersambung….






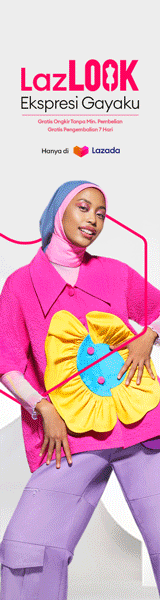










Tinggalkan Balasan