📣 Ikuti saluran resmi WhatsApp kami sebelum membaca berita!
Join WhatsAppNgada, katasulsel.com — Negara ini rajin berpidato soal masa depan. Tentang bonus demografi. Tentang Indonesia Emas 2045. Tentang generasi unggul dan SDM berkualitas.
Tapi di Nusa Tenggara Timur (NTT), seorang murid SD berusia 10 tahun menggantung diri karena tak mampu membeli buku dan pena atau pulpen.
Ya, cuma buku dan pena. Bukan laptop. Bukan pula tablet. Bukan kuota internet. Hanya alat tulis paling dasar yang bahkan sering dijadikan bonus belanja di toko.
Harga totalnya sekitar Rp10 ribu.
Jumlah itu mungkin tak cukup untuk parkir mobil pejabat. Bahkan tak cukup untuk membeli es kopi susu ukuran tanggung di Jakarta. Tapi bagi seorang anak SD di Kabupaten Ngada, NTT, angka itu berubah menjadi tembok. Tinggi. Dingin. Tak bisa dilompati.
Anak itu memilih mati.
Yang lebih menyayat, ia sempat menulis surat. Untuk ibunya. Isinya bukan protes. Bukan kemarahan. Isinya justru menenangkan. Ia meminta ibunya tidak menangis.
Seorang anak 10 tahun, menyiapkan kepergiannya sendiri dengan empati yang bahkan sering tak dimiliki orang dewasa.
Di titik ini, tragedi ini berhenti menjadi kisah keluarga miskin. Ini adalah potret negara yang gagal hadir di ruang paling sunyi: ruang batin anak miskin.
Kita sering berdebat soal kurikulum merdeka. Soal asesmen nasional. Soal ranking PISA. Tapi kita lupa satu hal paling mendasar: masih ada anak yang menganggap sekolah sebagai beban mematikan karena tak sanggup membeli pena.
Sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak miskin. Tapi dalam kasus ini, sekolah justru menjadi sumber tekanan. Bukan karena guru jahat. Bukan karena teman mengejek. Tapi karena sistem membiarkan anak menanggung malu sendirian.
Negara selalu datang belakangan. Setelah mayat ditemukan. Setelah berita viral. Setelah publik marah. Menteri menyampaikan duka. Pemerintah menjanjikan evaluasi data kemiskinan. Semua kalimatnya rapi. Semua niatnya terdengar baik.
Tapi satu anak sudah mati.
Pertanyaannya sederhana tapi memalukan: di mana negara sebelum tali itu melilit leher seorang murid SD?
Mengapa kemiskinan masih harus dibuktikan dengan kematian agar dianggap serius? Mengapa bantuan sosial baru bergerak setelah tragedi, bukan sebelum?
Ini bukan soal NTT semata. Ini cermin nasional. Tentang betapa jauhnya kebijakan pendidikan dari realitas paling dasar. Tentang betapa mudahnya kita bicara “pendidikan gratis” sambil menutup mata pada biaya-biaya kecil yang justru paling mematikan bagi yang paling miskin.
Indonesia kehilangan satu anak. Bukan karena bencana alam. Bukan karena wabah. Tapi karena sebuah pena.
Dan itu bukan tragedi.
Itu tamparan. (*)




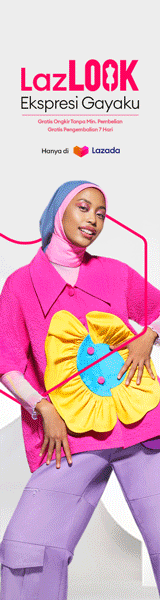










Tinggalkan Balasan