📣 Ikuti saluran resmi WhatsApp kami sebelum membaca berita!
Join WhatsAppEnrekang, katasulsel.com — Kota kecil seharusnya mudah ditata. Tapi Enrekang justru memberi contoh sebaliknya: trotoar yang semestinya jadi “rumah aman” pejalan kaki, berubah fungsi menjadi etalase dagangan permanen.
Ada meja, ada tenda, ada gardu. Lengkap. Tinggal pasang papan nama: Trotoar Rasa Pasar.
Pejalan kaki? Silakan minggir. Kalau perlu turun ke aspal. Berbagi ruang dengan motor dan mobil. Urusan selamat atau tidak, itu risiko pribadi.
Pemandangan ini bukan satu dua titik. Di jantung kota, trotoar tak lagi bisa disebut trotoar. Ia lebih mirip perpanjangan kios. Kumuh, sempit, dan berbahaya. Bagi pengendara, lapak-lapak itu juga jadi “tirai” yang menutup pandangan. Rawan kecelakaan. Tapi entah kenapa, seolah semua baik-baik saja.
Yang menarik, negara sebenarnya sudah menyiapkan perangkatnya. Ada Satpol PP—lengkap dengan atribut dan kewenangan. Ada Dinas Lingkungan Hidup—penjaga estetika dan kebersihan kota. Ada undang-undang—jelas, tegas, dan tak multitafsir.
Namun di Enrekang, trotoar tetap dikuasai PKL permanen. Pertanyaannya sederhana: apakah aturan kalah oleh kebiasaan?
Satpol PP punya mandat menertibkan. Tapi yang tampak justru pembiaran panjang. Bukan sehari dua hari. Lapak-lapak itu berdiri kokoh, seolah punya IMB emosional: “sudah lama di sini”.
DLH pun tak bisa cuci tangan. Trotoar kumuh, sampah aktivitas dagang, visual kota yang semrawut—itu wilayah mereka. Kepala DLH Enrekang, Yarsin Gau, akhirnya angkat bicara.
“Kami akan turun melakukan sosialisasi persuasif. Terutama PKL yang mempermanenkan lapak di trotoar. Itu jelas melanggar dan harus ditertibkan,” ujarnya, Senin (2/2/2026).
Kata kuncinya: akan. Publik tentu berharap bukan sekadar wacana rutin. Sosialisasi penting, tapi trotoar bukan ruang kompromi tanpa batas. Ada hak pejalan kaki yang selama ini terampas.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah terang benderang. Pasal 131 menjamin trotoar untuk pejalan kaki. Pasal 274 dan 275 memberi sanksi bagi siapa pun yang mengganggu fungsi jalan. Negara sudah bicara. Tinggal pemerintah daerah mau mendengar atau tidak.
Warga pun lelah. “Kami ingin Enrekang rapi, indah, dan aman,” kata seorang warga pusat kota. Kalimat sederhana, tapi mengandung kritik keras: kota ini bisa lebih baik, kalau mau.
Trotoar bukan soal PKL versus pejalan kaki. Ini soal keberanian pemerintah menegakkan aturan secara adil. Menata, bukan mematikan. Mengatur, bukan membiarkan.
Kalau trotoar saja tak bisa diselamatkan, jangan heran kalau warga akhirnya belajar satu hal: di Enrekang, berjalan kaki memang bukan prioritas.
(ZF)




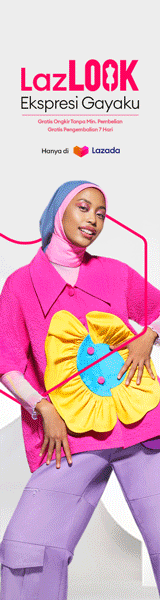










Tinggalkan Balasan