Fenomena FOMO Kosmetik dan Gempuran Produk Xenobiotik di Kalangan Remaja
 Syamsul Bahri
Syamsul BahriBy : Syamsul Bahri
Dosen Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo
Jika ada satu ledakan sosial yang paling sunyi tapi paling mematikan, barangkali itulah rak-rak kosmetik di marketplace: sunyi ketika dibeli, mematikan ketika dipakai. Para remaja kita bahkan tak sempat membaca komposisi yang diprint kecil sekali—lebih kecil daripada rasa takut mereka ketinggalan tren. Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) di dunia kosmetik menjelma menjadi arus deras yang bukan hanya didorong keinginan tampil cantik, tetapi juga ketakutan hidup tidak terlihat.
Di sudut inilah nama BPOM dan Dinas Kesehatan sering disebut seperti dua penjaga gerbang yang kewalahan menghadapi pasukan produk xenobiotik—bahan asing bagi tubuh—yang datang tanpa henti, tanpa permisi. Kita menyebutnya “kosmetik ilegal”, “skincare palsu”, atau “pemutih instan”. Namun para remaja punya sebutan lain yang lebih simpel: “yang lagi viral.”
BPOM sejatinya bukan sekadar lembaga yang memberi cap “aman” pada sebuah produk. Ia adalah benteng terakhir. Kebijakan, pengawasan laboratorium, izin edar, hingga penegakan hukum—semuanya dirangkai seperti sebuah sistem pertahanan bertingkat. Tidak ada produk kosmetik seharusnya lolos ke tangan publik tanpa melewati kokohnya gerbang ini. Namun dunia digital punya kecepatan sendiri. Produk ilegal bisa muncul malam ini, viral pagi besok, dan dibeli ribuan remaja sore harinya. Kecepatan seperti itu tidak pernah ada dalam buku panduan pemerintahan.
Di tingkat daerah, Dinas Kesehatan memikul beban yang lebih manusiawi: berhadapan langsung dengan kasusnya. Remaja yang wajahnya melepuh karena krim bermerkuri, ibu-ibu yang ketergantungan krim pemutih tanpa label, hingga pedagang kecil yang tak tahu bahwa barangnya melanggar hukum. Dinkes mesti bertindak cepat: razia, edukasi, pelaporan ke BPOM, hingga sosialisasi di sekolah-sekolah. Dalam banyak kasus, Dinkes-lah yang pertama kali mendengar berita bahwa sebuah krim “viral” ternyata berbahaya. Dan acapkali, berita itu terlambat beberapa minggu setelah puluhan wajah remaja menjadi korban eksperimen industri gelap.
Fenomena FOMO kosmetik menambah ruwet keadaan. Media sosial telah membentuk laboratorium raksasa tanpa etika. Influencer mengoleskan krim ke wajahnya sambil tersenyum, dan itu cukup untuk meyakinkan ratusan ribu remaja bahwa produk itu bekerja. Mereka percaya pada hasil instan. Mereka percaya pada cahaya ring light yang memantul di wajah sang idola. Yang tidak mereka baca adalah kandungannya: merkuri, hidrokuinon dosis tinggi, atau xenobiotik lain yang tidak pernah dirancang untuk kulit manusia.
Kasus-kasus kerusakan kulit kini seperti cerita standar: wajah yang memutih cepat lalu mendadak memerah, timbul rasa panas, kemudian muncul ketergantungan. Ada yang harus menjalani perawatan medis jangka panjang. Ada pula yang tak berani keluar rumah karena kerusakan pigmen. Dan ironisnya, semua itu bermula dari ketakutan sederhana: takut terlihat “tidak mengikuti zaman.”
Di tengah hiruk-pikuk itu, BPOM berusaha memperkuat garda edukasi. Mereka melibatkan generasi muda sebagai duta keselamatan produk, membangun literasi agar remaja mulai bertanya sebelum membeli. Dinkes di daerah pun melakukan hal serupa: masuk ke sekolah-sekolah, mengingatkan bahwa kulit mereka bukan tempat percobaan. Tetapi di luar ruang kelas, algoritma media sosial terus bekerja. Remaja kembali diserbu video “sebelum-sesudah” yang ajaibnya mampu mengganti akal sehat hanya dengan durasi 15 detik.
Dalam kegaduhan ini, kita seperti sedang menghadapi dua dunia: dunia institusional yang bergerak dengan prosedur, dan dunia digital yang bergerak dengan kecepatan bola api. Ketika keduanya bertemu, selalu ada korban—umumnya mereka yang paling muda, paling labil, dan paling mudah terpesona.
Sungguh mengherankan bahwa generasi yang lahir dengan akses internet justru menjadi generasi yang paling mudah diperdaya. Mereka sangat mahir membuat konten, namun sering kali gagap memeriksa label izin edar. Mereka bisa membedakan filter kamera, namun tak mampu membedakan krim asli dari racikan rumahan. Dan yang paling ironis: mereka ingin tampil glowing, tetapi justru terjerumus dalam produk yang merusak jaringan sel mereka sendiri.
Di titik ini, peran orang tua mestinya tidak kalah penting dari BPOM atau Dinkes. Remaja membutuhkan tempat bertanya sebelum membeli. Mereka membutuhkan seseorang yang mengajarkan bahwa “cantik” tidak sama dengan “cerah dalam tiga hari”. Tetapi banyak orang tua pun tak cukup paham. Bahkan ada ibu-ibu yang ikut membeli produk viral itu lebih dulu daripada anaknya.
Sementara itu, industri gelap kosmetik berkembang seperti semak belukar: ditebang di satu tempat, tumbuh di tempat lain. Dilarang di satu platform, muncul di platform berikutnya. Itulah sebabnya kolaborasi BPOM dan Dinkes tidak boleh hanya sebatas razia dan imbauan. Ia harus naik kelas: literasi publik yang terus-menerus, kerja sama lintas platform digital, dan penindakan hukum yang tidak menyisakan ruang abu-abu bagi pelaku.
Karena selama masih ada remaja yang merasa “harus” glowing agar diterima, selama itu pula pasar kosmetik ilegal akan subur. Selama masih ada pedagang yang tergiur untung cepat, selama itu pula merkuri akan mencari wajah baru untuk dirusak.
Pada akhirnya, gempuran produk xenobiotik ini bukan semata persoalan kesehatan. Ia adalah potret hubungan rapuh antara teknologi, perilaku sosial, dan regulasi negara. Kita membutuhkan BPOM dan Dinkes sebagai tembok perlindungan, tetapi kita juga membutuhkan masyarakat yang lebih melek, remaja yang lebih kritis, orang tua yang lebih peduli, serta influencer yang lebih bertanggung jawab.
Sebab tidak ada lembaga pengawas di dunia—sekuat apa pun—yang mampu mengawasi keinginan manusia untuk terlihat sempurna. Hanya literasi yang dapat melunakkannya, dan hanya kesadaran yang dapat menyelamatkan mereka dari bahaya yang dibungkus glitter kecantikan. (*)
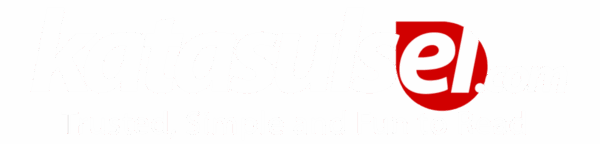


















Tidak ada komentar