Roslan Bicara Hipertensi, Kutlu Bicara Dunia, Seminar Kesehatan Internasional dari Bulukumba dan Konawe Selatan (Hari-1)
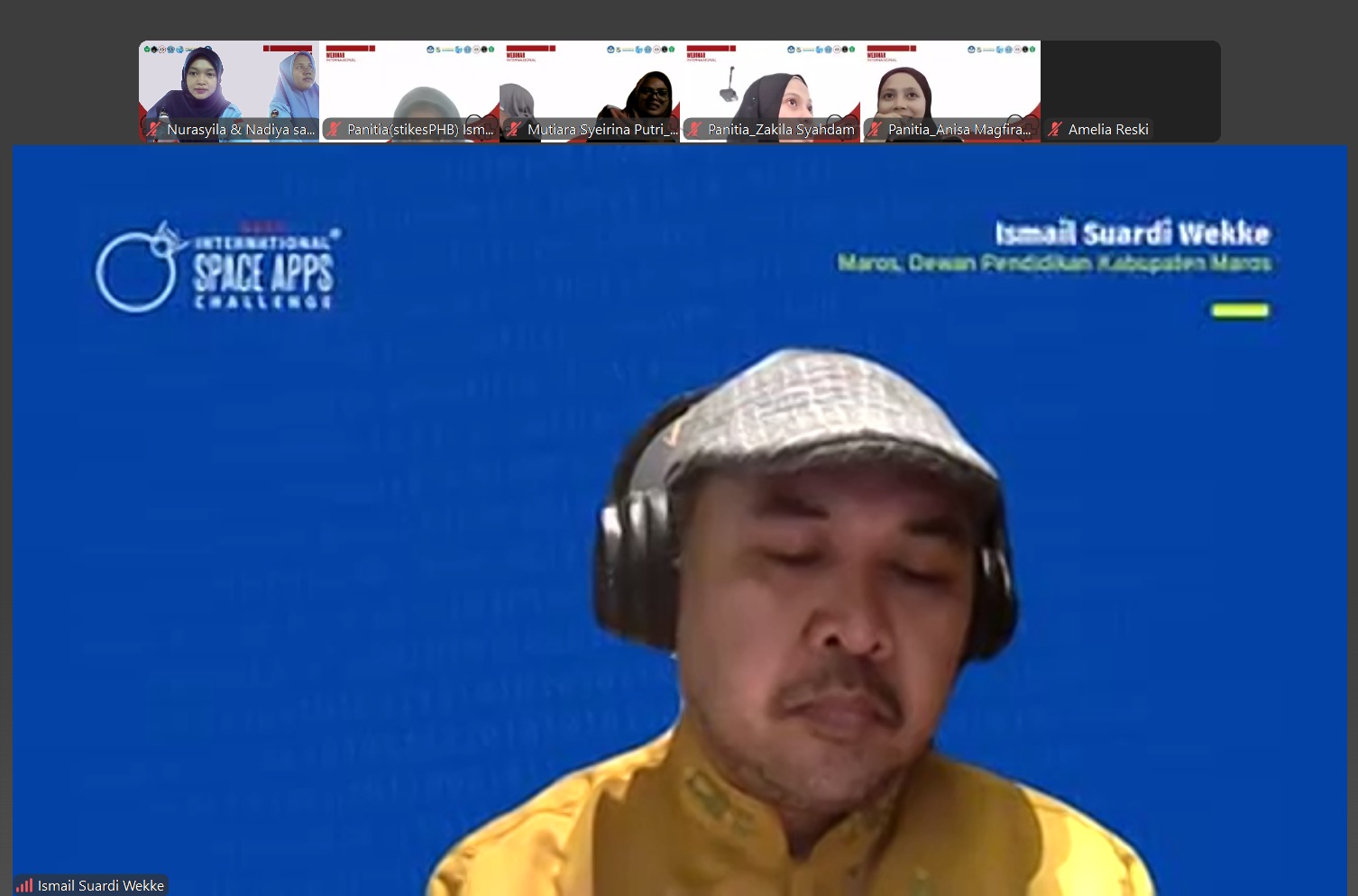
Penulis: Edy Basri
Di layar Zoom yang memantul di kacamata para peserta, seorang profesor dari Malaysia bicara soal hipertensi. Tapi cara ia mengemasnya membuat detak jantung audiens justru melambat: santai, runtut, dan dalam. Namanya Prof. Madya Ts. Dr. Roslan Bin Umar. Judul materinya terdengar seperti puisi kosmik: From Deep Water to Deep Space. Tapi isi presentasinya sangat membumi. Bahkan sangat dapur.
Ia bercerita bagaimana Universitas Muslim Indonesia melahirkan delapan karya ilmiah tentang keperawatan keluarga, semua sudah bersertifikat HAKI. Modul ajar. Panduan praktik. Buku saku. Bahkan panduan mengevaluasi hasil perawatan. Semua dengan satu tujuan: agar keluarga di rumah bisa menjadi perawat pertama—dan terbaik—bagi pasien hipertensi.
Kalau ada yang berpikir ini seminar yang terlalu teoritis, pemateri kedua membuatnya berpikir ulang. Dr. Berry Juliandi dari IPB bukan cuma tampil dengan slide yang penuh warna. Ia datang dengan data, semangat, dan satu peringatan: kalau kita tidak paham biodiversitas kita sendiri, jangan heran kalau orang lain yang nanti mengklaimnya.
Berry menunjukkan bagaimana bentuk sayap lebah bisa dipecah menjadi data. Bagaimana lekuk duduk monyet Sulawesi bisa jadi identitas spesies. Dan bagaimana wajah-wajah kita, manusia Indonesia, menyimpan cerita panjang migrasi dan evolusi yang belum selesai dibaca. Di tangan Berry, bioinformatika dan AI bukan sekadar istilah. Mereka adalah alat untuk melestarikan, bukan hanya untuk memprediksi.
Lalu datanglah pembicara ketiga. Prof. Dr. Onder Kutlu dari Turki. Ia seperti datang dari ruang kuliah filsafat internasional. Tapi ucapannya menohok: PBB bukan lagi penjaga perdamaian. Tapi klub eksklusif lima negara besar yang terus memveto masa depan dunia.
Onder bicara bukan hanya tentang lingkungan dan kesehatan, tapi tentang ketimpangan kekuasaan global. Tentang veto yang membungkam, dan tentang negara-negara kecil yang hanya bisa menonton sambil berharap. “Reformasi harus datang dari tekanan global,” katanya. Sebuah seruan yang entah didengar atau tidak oleh mereka yang sedang duduk nyaman di markas New York sana.
Tapi yang membuat hari pertama seminar ini terasa lain, justru bukan para pembicaranya. Melainkan tempat mereka didengar. Dua kampus dari timur Indonesia—STIKES Panrita Husada dan IAI Rawa Aopa—menjadi tuan rumahnya. Lewat Zoom, mereka menyatukan suara dari lima negara. Dari Sulawesi sampai Wales. Dari Malaysia sampai Istanbul. Di sela sinyal yang kadang patah-patah, diskusi-diskusi serius terjadi. Penuh hormat. Penuh gagasan.
Di ruang digital itu, batas negara menghilang. Bahkan batas antara kampus besar dan kecil pun lenyap. Yang ada hanya para pemikir, para pendengar, dan semangat berbagi. Mungkin beginilah glokalisasi sejatinya bekerja: ketika pengetahuan dari pojok desa bisa bersanding setara dengan teori dari pusat kota dunia.
Webinar ini bukan sekadar kegiatan ilmiah. Ia adalah bukti bahwa kampus kecil pun bisa menjadi panggung besar, asal punya kemauan untuk membuka jendela. Dan jendela itu kini tak perlu lagi dibuat dari beton. Cukup dengan sinyal, niat, dan semangat bertanya.
Esok, webinar ini akan berlanjut. Materi baru, ide-ide baru. Tapi satu hal yang mungkin tetap sama: langit dan laut akan kembali bertemu di layar. Dan dari Zoom, kampus-kampus di Timur Indonesia kembali menyuarakan bahwa mereka ada. Dan berpikir. Dan menghubungkan dunia. (*)



















Tidak ada komentar