📣 Ikuti saluran resmi WhatsApp kami sebelum membaca berita!
Join WhatsAppLuwu Timur, Katasulsel.com — Selama lebih dari dua dekade, warga Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, menggantungkan hidup dari lahan yang mereka buka dan kelola sendiri.
Tanah itu ditanami, diwariskan antar-generasi, serta setiap tahun dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya kepada negara.
Namun pada 2024, lahan seluas 3.945.000 meter persegi atau 394,5 hektare itu tiba-tiba dinyatakan sebagai aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mlalui Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dan telah dipersewakan kepada PT IHIP sebagai kawasan industri berstatus Program Strategis Nasional (PSN).
Kini warga yang telah lama bermukim dan bercocok tanam di atasnya diminta segera meninggalkan lokasi.
Bagi warga, ini bukan sekadar persoalan sertifikat. Ini menyangkut sejarah penguasaan, pengakuan administratif selama bertahun-tahun, dan pertanyaan tentang ke mana hukum berpihak.
*Lahan Digarap, Pajak Dibayar*
Sejak akhir 1990-an, warga mulai membuka dan mengelola lahan di Desa Harapan. Seiring waktu, mereka mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) dari pemerintah desa dan secara rutin membayar PBB.
“Kami bayar pajak ke pemerintah. Tapi ketika kami minta kepastian hukum, justru kami disuruh pergi,” ujar Ancong Taruna Negara, salah satu warga.
Bagi warga, penerbitan SKT serta pembayaran pajak selama bertahun-tahun menjadi bukti bahwa keberadaan mereka diakui secara administratif, meski belum memiliki sertifikat hak milik.
Mereka menilai, penguasaan fisik yang berlangsung puluhan tahun tidak bisa dihapus hanya dengan satu dokumen administratif.
*Klaim Pemda: SKT dan PBB Bukan Alas Hak*
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersikukuh pada posisinya. Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, menegaskan lahan tersebut adalah milik pemerintah daerah.
“Iya kan tanahnya Pemda,” ujarnya.
Menurut Ramadhan, SKT dan bukti pembayaran PBB tidak dapat dijadikan alas hak kepemilikan.
“SKT dan PBB bukan bukti kepemilikan,” tegasnya.
Karena itu, menurutnya, warga seharusnya meninggalkan lokasi karena tidak memiliki dasar hukum atas tanah tersebut.
“Seharusnya dia meninggalkan tempat karena tidak ada alas haknya,” kata Ramadhan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penyelesaian melalui jalur pengadilan, ia menjawab singkat, “Hukum apa lagi, sudah jelas.”
*Sengketa Objek: Identik atau Berbeda?*
Salah satu inti persoalan terletak pada objek lahan yang disertifikatkan. Warga mempertanyakan apakah lahan yang tercantum dalam HPL tahun 2024 benar-benar identik dengan lahan kompensasi yang disebut-sebut berasal dari PT Inco—kini PT Vale Indonesia Tbk—pada 2006.
Perbandingan peta lahan kompensasi 2006 dengan peta HPL 2024 menunjukkan adanya perbedaan bentuk dan batas yang dinilai signifikan oleh warga.
Ketika ditanya apakah perbedaan tersebut hanya klaim sepihak warga, Ramadhan menjawab, “Klaim aja.”
Namun saat dikonfrontasi dengan dua peta berbeda, ia mengakui kemungkinan adanya pergeseran.
“Bergeser mungkin dua hektare saja. Setelah pelepasan Vale disertifikatkan Pemda melalui Kementerian ATR,” ujarnya.
Bagi warga, pergeseran sekecil apa pun berarti objeknya tidak identik. Dalam sengketa pertanahan, ketepatan batas dan lokasi menjadi aspek krusial.
*Mengapa Baru Disertifikatkan pada 2024?*
Pertanyaan lain yang mengemuka adalah mengapa lahan yang disebut sebagai aset daerah sejak 2006 baru disertifikatkan pada 2024.
Ramadhan menjelaskan bahwa proses administratif penyerahan aset baru rampung beberapa tahun terakhir.
“Tidak NPHD-nya 2022,” katanya, merujuk pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi syarat formal pendaftaran aset atas nama pemerintah daerah.
Ia menambahkan, hingga 2022 lahan tersebut masih dikuasai pihak perusahaan. “Sampai tahun 2022 masih dikuasai Vale,” ujarnya.
Artinya, meski disebut sebagai lahan kompensasi sejak 2006, proses pelepasan dan pendaftaran formal baru tuntas belasan tahun kemudian.
*Kritik LBH: Harus Diuji di Pengadilan*
Ketegangan meningkat ketika aparat memasang papan klaim kepemilikan Pemda di atas lahan yang selama ini dikuasai warga.
Kuasa hukum warga dari YLBHI LBH Makassar, Hasbi, menilai langkah tersebut berpotensi melanggar prinsip negara hukum.
“Jika pemerintah daerah mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya, maka seharusnya dibuktikan melalui mekanisme hukum di pengadilan, bukan dengan penertiban sepihak,” ujarnya.
Menurutnya, penguasaan lahan oleh warga selama puluhan tahun tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Penggusuran tanpa putusan pengadilan berpotensi melanggar hukum dan hak asasi manusia,” tegasnya.
*Di Antara Sertifikat dan Sejarah Penguasaan*
Sengketa di Desa Harapan memperlihatkan ketegangan klasik antara legalitas administratif dan realitas penguasaan di lapangan.
Di satu sisi, pemerintah memegang Sertifikat Hak Pengelolaan yang sah secara formal. Di sisi lain, warga memiliki sejarah penguasaan fisik, SKT, serta bukti pembayaran pajak yang berlangsung lebih dari dua dekade.
Hingga kini, belum ada putusan pengadilan yang secara definitif menentukan siapa yang berhak secara hukum atas lahan tersebut.
Yang terjadi adalah klaim administratif berhadapan langsung dengan keberatan warga—tanpa proses adjudikasi yang mempertemukan kedua pihak dalam ruang hukum yang setara.
Selama belum diuji di pengadilan, sertifikat HPL akan tetap menjadi dasar klaim Pemda, sementara sejarah penguasaan warga akan terus menjadi dasar keberatan mereka.
Di Desa Harapan, persoalannya bukan semata siapa yang memegang sertifikat. Melainkan, apakah sengketa tanah ini akan diselesaikan melalui proses hukum yang terbuka dan adil, atau cukup dengan perintah untuk meninggalkan tanah yang telah digarap seumur hidup? (*)






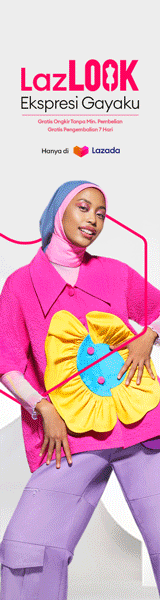










Tinggalkan Balasan