JIKA sejarah bisa berbicara, niscaya ia akan memanggil nama Nene’ Mallomo setiap kali cerita tentang keadilan dan ketegasan diperbincangkan.
Di abad ke-16, ketika kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Selatan masih menganyam keseharian mereka dari sawah, ladang, dan perdagangan sederhana, seorang manusia bernama La Pagala muncul bukan sekadar sebagai penasihat, tetapi sebagai simbol teguhnya integritas hukum.
Orang Bugis menamai dia Nene’ Mallomo: ‘nene’ berarti orang yang dituakan dan dihormati, ‘mallomo’ berarti pemberi kemudahan.
Dalam bahasa sehari-hari, ia adalah figur yang memberi jalan, sekaligus menjaga aturan. Tapi jangan salah: ia juga hakim yang tegas, yang berani menegakkan hukum bahkan kepada anak kandungnya sendiri.
La Pagala lahir di tengah dinamika Kerajaan Sidenreng, yang saat itu dipimpin Raja La Patiroi. Raja yang visioner itu menempatkan La Pagala sebagai penasihat sekaligus hakim kerajaan, memercayakan kesejahteraan rakyat di tangannya.
Dan La Pagala, dengan ketajaman akal dan hati yang disiplin, memastikan kesejahteraan itu bukan retorika kosong.
Siapa yang mengelola kerajaan? Raja La Patiroi dan Nene’ Mallomo. Rakyat, tentu saja, menjadi saksi dari kemakmuran yang lahir dari kerja keras dan integritas. Hasil bumi melimpah, ternak sehat, dan masyarakat hidup dalam kecukupan.
Sebuah falsafah Bugis, “Resopa temmangingi namalomo naletei pammase dewata”, hidup di antara mereka: kerja keras adalah pintu menuju keberkahan Tuhan.
Namun, setiap kisah besar selalu memiliki bayangan. Tiga tahun kemudian, kemarau panjang menyelimuti Sidenreng. Sawah mengering, ladang retak, ternak kurus, bahkan mati. Rakyat mulai resah, cemas, dan berbisik di sudut-sudut rumah panggung mereka. Raja La Patiroi memanggil Nene’ Mallomo.
“Mallomo, apa yang terjadi dengan kerajaan kita?” tanya sang raja dengan nada getir.
Nene’ Mallomo, dengan wajah tenang tapi mata menyorot tajam, menjawab, “Raja, ini bukan sekadar alam. Ada pelanggaran hukum adat yang membuat Tuhan murka.”
Apa pelanggaran itu? Penyelidikan dilakukan dengan teliti. Dalam kerajaan, hukum adat adalah urat nadi kehidupan; setiap pelanggaran tak bisa diabaikan.
Hasilnya mengejutkan: pelanggar adalah putra kandung Nene’ Mallomo sendiri. Seorang pemuda yang, tiga tahun lalu, mengambil sebatang kayu milik tetangga untuk memperbaiki sisir salaganya yang patah saat membajak sawah.
Bayangkan ketegangan itu: seorang ayah yang harus memutuskan nasib anaknya di hadapan raja, rakyat, dan hukum adat yang mengikat semua orang tanpa pandang bulu.
Di ruang sidang kerajaan, Nene’ Mallomo berdiri. Putranya di hadapannya, menunduk, menunggu putusan. “Kamu benar-benar melakukan ini?” tanya Nene’ Mallomo, nada suaranya datar tapi menggigit.
“Iya, ayah. Saya hanya ingin memperbaiki sisir salaga saya,” jawab sang anak, suaranya nyaris tak terdengar.
Suasana hening. Raja La Patiroi menatap tajam, berdebat dalam hati antara kasih sayang dan prinsip. Nene’ Mallomo tetap teguh. Menurutnya, akibat tindakan anaknya, seluruh kerajaan mengalami penderitaan. Hukum harus ditegakkan. Hukuman mati diputuskan.
Raja Patiroi sempat memohon: “Mallomo, bisakah kau menganulir putusan itu? Jangan biarkan darah anak sendiri tercurah.”
Nene’ Mallomo menggeleng. “Raja, hukum tidak mengenal keluarga. Anak atau rakyat, semua sama di hadapan adat. Ini harus dilakukan demi keselamatan kerajaan.”
Sebelum eksekusi, Nene’ Mallomo memerintahkan putranya memohon maaf kepada seluruh rakyat. Adegan itu, menurut catatan lisan, berlangsung dengan hening yang mencekam: seorang putra mengulurkan tangan ke rakyatnya, menunduk, dan mengakui kesalahannya.
Hanya setelah itu, hukum dijalankan. Dan secara ajaib, Bumi Sidenreng kembali sejahtera: hujan turun, sawah hijau, ternak gemuk, dan rakyat kembali makmur.
Mengapa kisah ini penting untuk kita hari ini? Dari tragedi dan ketegasan itu lahir prinsip Bugis: “Nennia Adek’e Temmakkeana Temmakkeappo”, yang berarti hukum tak mengenal anak, cucu, atau kedudukan; persamaan di hadapan hukum adalah mutlak. Nilai itu menembus waktu, menginspirasi hakim-hakim modern di Indonesia.
Dari perspektif sosial, kisah Nene’ Mallomo menunjukkan bahwa integritas hukum dan disiplin sosial lebih besar daripada ikatan keluarga.
Dalam masyarakat agraris seperti Sidenreng saat itu, pelanggaran kecil bisa menimbulkan konsekuensi kolektif: satu batang kayu bisa menjadi pemicu bencana alam dan sosial. Maka hukum adat bukan sekadar aturan; ia adalah pelindung kesejahteraan bersama.
Secara psikologis, tindakan Nene’ Mallomo menunjukkan keseimbangan luar biasa antara kasih sayang dan ketegasan.
Tidak ada ruang untuk kompromi, tapi juga ada ruang untuk refleksi dan tanggung jawab. Putranya pun, melalui proses ini, belajar menghormati hukum dan adat, memahami bahwa kebaikan pribadi tidak boleh merugikan kebaikan bersama.
Filosofi Bugis yang melekat dalam kisah ini—“Resopa temmangingi namalomo naletei pammase dewata”—mengajarkan bahwa kerja keras dan disiplin bukan hanya untuk kesejahteraan diri, tetapi juga untuk harmoni sosial dan restu Tuhan. Integritas individu tercermin dalam kesejahteraan kolektif.
Efek jangka panjangnya? Puluhan generasi kemudian, masyarakat Sidenreng tetap menghormati prinsip yang sama. Ketegasan hukum, keberanian menegakkan aturan, dan integritas tetap menjadi nilai yang diwariskan.
Kisah Nene’ Mallomo menjadi cerita wajib di setiap pendidikan adat Bugis dan menjadi inspirasi bagi penegak hukum modern, termasuk hakim dan aparat pemerintah di Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, kisah ini membuka refleksi yang lebih luas bagi Indonesia: bagaimana menegakkan hukum tanpa kompromi di tengah tekanan sosial, politik, atau keluarga.
Bersambung…
Nene’ Mallomo mengingatkan kita bahwa hukum yang lemah akan merusak kesejahteraan kolektif. Hukum yang tegas, sekalipun menyakitkan individu, justru menyelamatkan komunitas.
Jika hari ini kita menatap koridor pengadilan atau ruang sidang, bayangkan bahwa nilai yang dipegang Nene’ Mallomo masih relevan: keadilan bukan hanya soal rasa, tapi soal prinsip, integritas, dan keberanian. Dalam sejarah Indonesia, figur seperti ini jarang, tapi pengaruhnya abadi.
Ratusan tahun telah berlalu, namun di Sidrap, di setiap pertemuan adat, di setiap pappaseng (falsafah hidup Bugis), nama Nene’ Mallomo tetap dikenang. Ia bukan sekadar legenda; ia cermin dari keadilan yang tidak mengenal kompromi, pengingat bahwa integritas tidak bisa ditawar, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Sejarah menyimpan kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menginspirasi. Seperti kata pepatah Bugis, “Hukum itu adalah nadi kehidupan; siapa yang meremehkannya, akan terseret arus bencana.” Nene’ Mallomo telah membuktikan: keadilan dan keberanian dalam menegakkan hukum dapat mengubah nasib rakyat dan bahkan menyeimbangkan alam.
Dan bagi Indonesia hari ini, inspirasi itu tetap hidup. Di ruang sidang, di meja hakim, di meja birokrat, kisah Nene’ Mallomo mengingatkan bahwa ketegasan bukan kejam, tapi penyelamat. Bahwa hukum yang ditegakkan dengan keberanian, keteguhan, dan integritas adalah hukum yang memberi kehidupan, bukan hanya bagi satu orang, tapi bagi seluruh komunitas.(*)




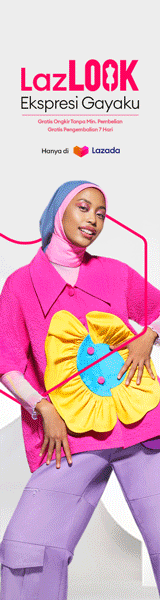










Tinggalkan Balasan