📣 Ikuti saluran resmi WhatsApp kami sebelum membaca berita!
Join WhatsAppPantai Raha kini aman, sawah menanti air, dan warga Muna tersenyum. Proyek pengamanan pantai dan bendungan mengubah kota perlahan—tapi nyata.
Laporan: Edy Basri
Pagi itu, saya berdiri di bibir Pantai Raha. Ombak menyapa lembut, tidak lagi liar seperti dulu. Ia patah di tembok beton panjang yang kini membentang 1,6 kilometer—tegak, kokoh, dan elegan. Tembok itu bukan sekadar beton, bukan sekadar batas fisik. Ia adalah garis hidup kota. Garis yang memberi warga rasa aman, ketenangan, dan harapan.
Di sekeliling saya, pasir masih basah karena air surut malam sebelumnya. Bau asin laut bercampur dengan aroma rumput liar yang tumbuh di pinggir pantai. Angin sepoi-sepoi menampar wajah, membawa percikan garam, dan suara burung camar yang berteriak riang. Dari kejauhan, perahu nelayan terlihat bergoyang ringan, menunggu hari yang cerah untuk melaut.
“Ini game changer,” kata Tayeb, tokoh muda Muna, sambil menunjuk pantai. Matanya bersinar. “Bukan cuma soal beton. Ini soal rasa aman, soal wajah kota yang berubah. Pantai sekarang hidup.”
Saya menoleh. Memang benar. Pantai ini bukan lagi zona waswas. Jalan utama kota, Masjid Agung Raha, rumah-rumah warga—dulu terancam gelombang dan rob—sekarang aman. Anak-anak berlarian di pasir basah, orang dewasa jogging, ada yang duduk di tepi tembok, menikmati angin dan suara laut. Bahkan beberapa muda-mudi tampak asyik nongkrong, selfie, dan bercanda.
Proyek pengamanan Pantai Muna ini digarap PT Pinar Jaya Perkasa dengan dukungan Kementerian PUPR dan BWS Sulawesi IV Kendari. Anggarannya Rp28 miliar dari APBN—kelihatan nyata, bukan sekadar angka di dokumen. Di Disway, proyek seperti ini disebut APBN yang kelihatan. Tidak abstrak. Tidak cuma di slide presentasi atau laporan rapat.

Saya berjalan menyusuri tembok beton, menapak di lantai yang masih hangat tersiram matahari pagi. Setiap langkah membuat pasir di bawah kaki berdecit halus. Seorang warga tua, Pak Arif, duduk di bangku kayu dekat pantai sambil mengamati ombak.
“Dulu takut tiap kali pasang,” katanya pelan. “Sekarang? Aman. Bisa duduk santai, ngobrol sama cucu tanpa khawatir air naik.”
Saya menatapnya. Senyum Pak Arif seperti melukiskan seluruh perubahan yang terjadi: nyata, sederhana, tapi mengena.
Di balik semua ini, ada tangan politik. Ridwan Bae, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, disebut menjadi pintu masuk proyek Kementerian PUPR ke Muna. Bersama Bupati Muna, Bachrun Labuta, mereka turun langsung meninjau lokasi. Mereka bukan sekadar hadir untuk foto atau seremoni. Mereka melihat langsung kondisi lapangan, menghitung risiko abrasi, berdialog dengan warga, bahkan menanyakan ke pekerja: “Bagaimana progresnya, aman tidak?”
Ridwan Bae menepuk bahu seorang pekerja. “Bagus. Beton rapi, anggaran tepat sasaran. Ini yang namanya APBN bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Bupati Muna, Bachrun Labuta, ikut tersenyum. “Pantai ini simbol perubahan. Warga bisa merasa aman, anak-anak bisa bermain, dan kota mulai punya wajah baru.”
Saya melihat ke arah ombak. Gelombang kecil menabrak tembok beton, tapi tidak ada lagi rasa takut. Hanya ketenangan yang terasa.
Bersambung…
Pantai yang dulu rawan kini menjadi ruang publik yang hidup. Sore hari, warga mulai berdatangan. Anak-anak bermain layang-layang, pasangan muda berfoto, pejalan kaki melintasi tembok panjang sambil berlari kecil. Aroma gorengan dan kopi pedagang kaki lima mulai tercium. Suara tawa bercampur debur ombak.
Seorang ibu muda, Fitri, duduk di pasir sambil mengawasi anaknya. “Dulu takut kalau anak-anak bermain di sini.
Sekarang? Bisa santai. Pantai hidup, nyaman. Bahkan keluarga bisa piknik di sini,” katanya sambil tersenyum.
Seorang pemuda lain, Hendra, berlari di tepi pantai. “Ini bikin kota kita terlihat lebih modern, tapi tetap ramah. Orang bisa sehat, jalan-jalan, santai. Pantai bukan lagi zona waswas, tapi zona hidup!”
Tayeb menambahkan: “Ini bukan cuma soal beton. Ini soal wajah kota. Warga bahagia, itu indikator sukses proyek. Dan saya lihat, mereka bahagia.”
Namun, cerita Muna tidak berhenti di pantai. Beberapa kilometer ke pedalaman, air sedang disiapkan untuk mengaliri sawah-sawah. Bendungan Laiba, di Kecamatan Parigi, telah tuntas. Sunyi, tidak ada potongan pita atau spanduk besar. Tapi dampaknya bisa panjang.

Saya menginjak tanah basah di sekitar bendungan. Aroma tanah campur air terasa kuat. Ikan kecil melompat di genangan air sementara burung bangau mencari makan. Petani mulai berdatangan, membawa cangkul, menatap air yang menggenang di bendungan.
“Ini simbol kepastian,” kata Tayeb. “Petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hujan. Musim tanam bisa dihitung. Risiko gagal panen ditekan.”
Rahmat, Humas BWS Sulawesi IV Kendari, menegaskan: “Proyek berjalan sesuai aturan. Bersih dari isu yang tidak berdasar. Fakta di lapangan jelas: pantai ramai hingga malam, sawah menunggu aliran air, wajah kota berganti. Itu yang paling penting.”
Air dari bendungan Laiba akan mengalir ke Kolasa, Labulubulu, dan sekitarnya. Saya mengikuti aliran sungai kecil dari bendungan. Pepohonan hijau menari ditiup angin, sawah mulai tampak bergairah.
Petani mulai menyiapkan bibit padi.
Pak Amir, petani lokal, tersenyum. “Dulu musim tanam harus berharap hujan. Sekarang? Bisa direncanakan. Air datang pasti. Panen lebih aman. Hidup lebih tenang.”
Seorang ibu, Ningsih, menambahkan sambil membawa keranjang kecil berisi sayuran: “Bendungan ini bukan simbol megah, tapi simbol kepastian. Ini yang kita tunggu-tunggu.”
Saya duduk di pinggir sawah. Matahari mulai naik. Suara burung, gemericik air, aroma tanah basah—semua menyatu. Di sini, pembangunan terasa bukan tentang megah, tapi tentang hidup manusiawi.
Pantai dijaga. Sawah dialiri. Dua proyek, satu nafas. Warga mulai merasakan manfaatnya sehari-hari. Anak-anak bermain tanpa takut, orang tua bisa santai, petani bisa menghitung musim tanam. Kota Muna perlahan berubah.
Bersambung…
Seorang guru, Ibu Ratna, berkata: “Anak-anak lebih bersemangat ke sekolah. Orang tua lebih tenang. Kota ini berubah pelan tapi nyata. Proyek bukan sekadar bangunan, tapi mengubah pola hidup.”
Seorang pedagang kaki lima, Pak Joko, tersenyum: “Sekarang pantai ramai sampai malam. Dagangan laris. Orang betah. Proyek ini membawa berkah ekonomi juga.”
Di sore hari, saya duduk bersama beberapa warga di tepi pantai. Tayeb tersenyum sambil menunjuk ombak.
“Kalau dulu laut seperti raksasa yang mau menelan kota. Sekarang? Laut sahabat. Dia tetap datang, tapi dengan tertib.”
Pak Arif menimpali: “Iya, dulu tiap kali pasang, saya bawa payung, bawa perahu cadangan. Sekarang? Cukup bawa kursi dan kopi. Ombak malah bikin adem.”
Tawa warga pecah. Seolah semua merayakan perubahan yang nyata, sederhana, tapi monumental bagi kehidupan mereka sehari-hari.
Pantai & Bendungan: Dua Simbol, Satu Nafas
Pantai dijaga. Sawah dialiri. Dua proyek berbeda, tapi satu nafas. Proyek ini bukan datang tiba-tiba. Ada tangan politik di belakangnya, ada dukungan APBN, tapi yang paling penting: dampaknya dirasakan langsung warga.
Seorang tokoh pemuda lain menambahkan: “Ini proyek yang membuktikan bahwa pembangunan bisa nyata. Bisa disentuh. Bukan hanya laporan atau janji. Orang bisa melihat sendiri.”
Di malam hari, Pantai Raha masih ramai. Lampu-lampu kecil dari warung kaki lima menyorot pasir, menciptakan suasana hangat. Angin laut membawa aroma kopi, gorengan, dan garam. Anak-anak masih berlarian, pasangan duduk berdua, dan beberapa muda-mudi selfie dengan tembok beton sebagai latar.
Sementara itu, sawah-sawah menanti air dari bendungan Laiba. Suara gemericik air dari sungai kecil terdengar menenangkan. Petani mulai menyiapkan ladang besok.
Di pedalaman, lampu-lampu kecil dari rumah warga menandakan malam yang damai. Kota ini, perlahan, sedang hidup.
Refleksi Akhir
Muna tidak bermimpi besar. Ia sedang bekerja pelan-pelan. Tapi perubahan itu—perlahan—sudah terasa. Pantai aman, sawah bergairah, warga tersenyum, kota memiliki wajah baru. Semua itu bukan sekadar pembangunan fisik, tapi pembangunan kehidupan.
Di sana, di pantai yang ramah, di sawah yang mulai menanti hujan buatan, Muna sedang belajar: pembangunan itu bukan hanya soal megah, tapi soal hidup yang lebih aman, lebih tenteram, dan lebih manusiawi.
Dan bagi saya, berdiri di bibir Pantai Raha, menatap tembok beton, mendengar debur ombak, mencium aroma tanah basah sawah, serta melihat senyum warga—semua itu adalah bukti bahwa Muna sedang berubah, perlahan, tapi pasti.
Pantai dijaga. Sawah dialiri. Kota Muna sedang berevolusi. (*)




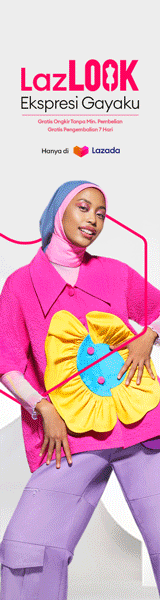










Tinggalkan Balasan