
Oleh: Dr. Maryono, S.Si, M.Si – Akademisi, Ketua Projo Sidrap
Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, 17 September 2021, sebuah kalimat meluncur dari bibir Menko Airlangga Hartarto. Kalimat itu sederhana, tapi punya denyut ideologis yang dalam: “Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia harus bergeser dari resource-driven menjadi innovation-driven.” Di balik kalimat itu, ada harapan yang ditambatkan: bahwa negeri ini, yang selama ini menggantungkan hidup dari menggali isi perut bumi, harus mulai menggunakan isi kepalanya.
Tiga tahun setelah itu, dunia tercengang. Dana Moneter Internasional (IMF) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-8 di dunia berdasarkan PDB dengan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP). Kita menyalip Inggris dan Prancis. Bukan karena tambang, bukan karena sawit semata—tetapi karena hilirisasi dan pengembangan green energy, energi masa depan yang tidak merusak bumi. Ini bukan dongeng, ini statistik.
Tapi seperti biasa, angka-angka di atas kertas seringkali tidak mencerminkan rasa lapar di dapur rakyat. Dua bulan setelah kabar gembira itu, 3 Maret 2025, BPS menyodorkan angka yang dingin: deflasi tahunan 0,09%. Ini bukan kabar baik. Ini alarm. Karena deflasi, meskipun berarti harga barang turun, sering kali menunjukkan satu hal yang lebih menakutkan: lesunya daya beli masyarakat.
Apa artinya? Artinya rakyat kita bukan tak mau belanja, tapi memang tak mampu. Dompetnya tipis. Pendapatannya menyusut. Dan ketika daya beli turun, maka roda ekonomi juga melambat. PHK mulai merebak, UMKM mulai sesak napas. Ironi dari sebuah pertumbuhan ekonomi yang—katanya—berkilau di atas kertas.
Dalam situasi semacam inilah, muncul sebuah gagasan yang tak biasa. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi dan UKM, melempar satu konsep yang menggetarkan akar rumput: Koperasi Desa. Bukan koperasi seperti biasanya. Bukan koperasi yang hanya mengurus simpan-pinjam dan berakhir macet. Ini koperasi dengan napas baru. Dengan semangat Merah Putih. Dan yang paling penting: disetujui langsung oleh Presiden Prabowo.
Akan ada 80.000 koperasi desa. Bukan angka asal sebut. Ini mesin raksasa. Mesin yang dirancang bukan untuk jalan di aspal, tapi untuk membajak lahan tandus ekonomi rakyat. Mesin yang dirakit dari partisipasi warga desa. Mesin yang diminyaki oleh semangat gotong royong. Mesin yang bukan hanya bicara tentang profit, tetapi tentang sustainability dan empowerment.
Secara teoritis, koperasi jenis ini mengandung tiga elemen penting pembangunan ekonomi: mendorong pertumbuhan ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Desa tak boleh lagi hanya jadi lumbung padi. Harus jadi basis produksi. Dari pertanian ke industri ringan. Dari bahan mentah ke barang jadi. Dari konsumtif ke produktif. Ini adalah transisi dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi transformasional.
Aktivitas ekonomi desa akan hidup kembali. UMKM disuntik modal, anak muda diajak jadi pelaku usaha. Mereka akan belajar manajemen usaha, literasi keuangan, dan keterampilan digital. Koperasi juga membuka peluang kerja, karena koperasi akan menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Ketika pasar merespons, lapangan kerja muncul.
Namun seperti apapun hebatnya mesin, jika operatornya tak terlatih dan panduan kerjanya kabur, maka kerusakan hanya tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, koperasi ini butuh sistem tata kelola yang prudential. Mulai dari SDM yang kompeten, sistem manajemen risiko yang adaptif, hingga financial governance yang transparan dan digitalisasi operasional. Tak boleh ada ruang untuk moral hazard atau inefisiensi sistemik.
Kata kuncinya: integrasi dan pengawasan. Harus ada sistem digital terpadu—integrated cooperative monitoring system—yang bisa mengawasi kinerja, aliran dana, dan dampak sosial secara real-time.
Kita tak sendirian. Dunia sudah memberi contoh. Lihat India. Di sana, koperasi bukan sekadar badan usaha. Tapi way of life. Koperasi seperti Amul Dairy dan HOPCOMS menjamin petani dan konsumen hidup layak. Produk susu, sayur, dan buah dijual dengan harga subsidi. Tapi tak membuat koperasi rugi. Karena skala dan efisiensi sistem mereka.
Perancis lain lagi. Di sana, koperasi menyumbang 12% dari PDB nasional. Kenapa bisa? Karena tata kelola mereka ketat. Ada audit independen. Ada sanksi. Ada reward. Pemerintah bukan hanya regulator, tapi juga fasilitator. Koperasi di Perancis adalah economic backbone—bukan hanya simbol sosial.
Akhirnya, kita kembali pada akar: desa. Di sanalah Indonesia lahir. Di sanalah kemandirian bisa dimulai. Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya kebijakan teknokratis. Ia adalah bentuk konkret dari ekonomi Pancasila—yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan hanya pasar.
Kalau koperasi ini berhasil, maka pertumbuhan 8% yang ditargetkan bukan lagi mimpi. Tapi jika gagal—karena korupsi, salah urus, atau sekadar asal-asalan—maka ia akan jadi catatan gagal lain dalam buku tebal sejarah pembangunan kita.
Jadi mari kita jaga. Dengan cinta, dengan ilmu, dan tentu saja: dengan pengawasan. (*)
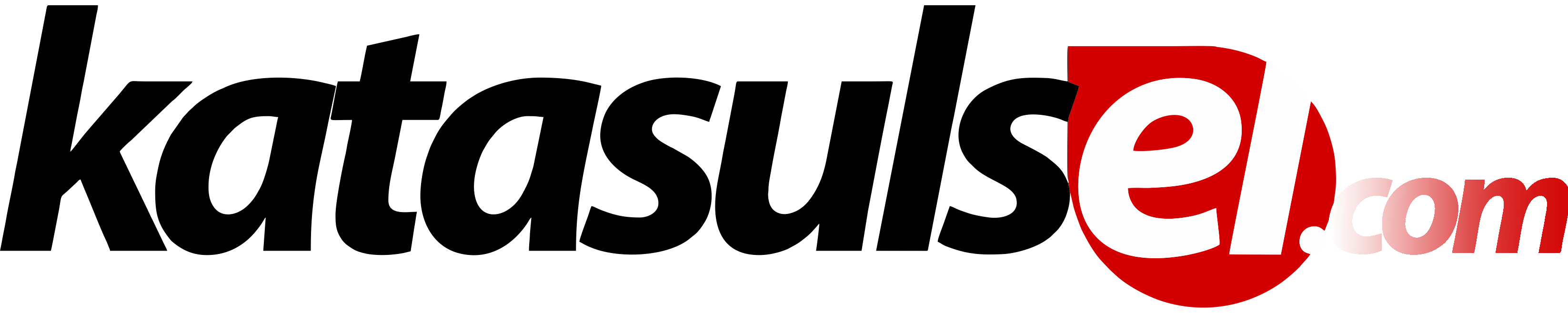







Tinggalkan Balasan