
Sidrap, Katasulsel.com — Angin pagi berhembus lembut dari arah Danau Sidenreng, mengantar aroma tanah basah dan harapan baru yang menyeruak dari batas-batas petak sawah. Di sela-sela percikan air dan gemeretak lumpur, langkah kaki seorang lelaki berpakaian dinas harian menyusuri pematang, dengan sepasang sepatu boot yang tak lagi bersih. Lelaki itu adalah Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif.
Beberapa jam sebelumnya, ia berdiri di atas panggung dalam forum Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu, menyampaikan visi besar soal kedaulatan pangan. Kini, ia berdiri di tengah petak sawah Desa Mojong, hanya 100 meter dari pesisir danau tempat sejarah Sidenreng bermula, bukan untuk memberi sambutan, melainkan untuk menanam.
Dengan tangannya sendiri, ia mengoperasikan alat tabela—direct seeding planter yang menjadi simbol modernisasi teknik tanam padi. Bukan canggung, bukan basa-basi. Gerakannya cekatan, seolah lumpur dan benih sudah akrab sejak lama. Sekali-kali ia menengok ke petani yang mengawasinya dari pinggir sawah. Mereka tersenyum, bukan karena protokoler, tapi karena mereka melihat dirinya sendiri dalam sosok pemimpin itu.
“Bismillah,” ucapnya lirih, nyaris lebih sebagai doa daripada pernyataan. Suara itu tenggelam dalam suara gemercik air, tapi maknanya bergema jauh. Karena tanam benih hari itu bukan sekadar ritual pembuka musim tanam kedua. Ia adalah penanda dimulainya fase kedua Sidrap sebagai laboratorium pangan nasional.
Musim tanam ini masuk dalam periode April–Juni, bagian dari strategi sistem IP 300 yang tengah didorong oleh pemerintah: intensifikasi pertanian dengan siklus tanam tiga kali setahun. Bukan tugas mudah, apalagi di tengah ancaman perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya. Tapi dengan pemimpin yang bersedia kotor, petani mana yang ragu untuk melangkah lebih jauh?
Matahari mulai naik perlahan ketika Syaharuddin menyeka keringatnya, berdiri tegak, lalu melihat hamparan sawah yang membentang luas. Tak ada gemuruh tepuk tangan atau kilatan kamera yang berlebihan. Hanya angin dan lumpur yang menjadi saksi bahwa hari itu, benih yang ditanam bukan cuma untuk panen, tetapi untuk harga diri daerah yang ingin kembali menjadi lumbung pangan Nusantara.
Di sinilah narasi itu berubah. Politik bukan hanya soal program dan data statistik, tetapi tentang keberanian masuk ke medan sesungguhnya. Syaharuddin mungkin tak akan menanam setiap hari, tapi satu kali turun sawah dengan hati yang utuh, cukup untuk menyemai ribuan semangat.
Sawah itu kini menyimpan lebih dari sekadar benih padi. Ia menyimpan harapan, keteladanan, dan pesan sunyi bahwa ketahanan pangan dimulai dari satu langkah kecil—satu tekad besar—di tengah lumpur yang bernama Indonesia.(*)
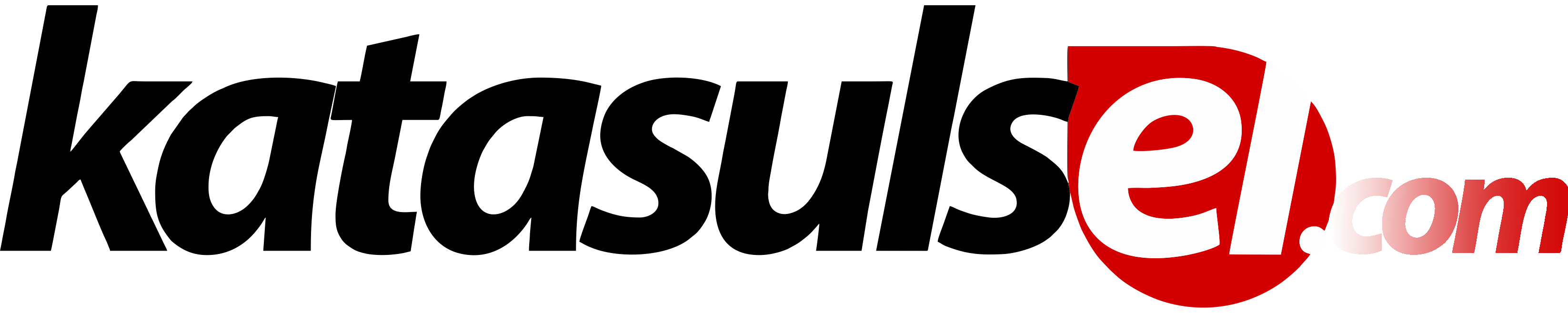














Tinggalkan Balasan