
Bandung, Katasulsel.com — Aroma kontroversi menyelimuti kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) seiring bergulirnya proses pemilihan rektor tahun ini.
Bukan soal siapa yang akan menduduki kursi tertinggi kampus, melainkan ihwal dasar hukumnya yang kini dipertanyakan sejumlah akademisi kampus Bumi Siliwangi.
Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UPI Nomor 1 Tahun 2025 menuai kritik tajam lantaran dianggap memangkas peran signifikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam proses pemilihan rektor.
Pasal 17 aturan tersebut menyebut bahwa setiap anggota MWA, termasuk Menteri, hanya memiliki satu suara. Padahal, Statuta UPI berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2014 menegaskan: suara Menteri setara 35 persen dari total suara.
“Ini bukan sekadar soal angka, ini soal prinsip,” ujar Elly Malihah, anggota Senat Akademik sekaligus guru besar Sosiologi Pendidikan UPI, Jumat, 25 April 2025.
Ia menyebut bahwa penyetaraan suara Menteri dengan anggota MWA lainnya adalah bentuk “pengebirian” terhadap mandat negara.
Menurut Elly, pemilihan rektor tak bisa dilihat sebagai satu titik akhir semata, melainkan rangkaian panjang yang meliputi penjaringan, penyaringan, hingga pemilihan. “Jika Menteri hanya dihitung satu suara dalam semua tahapan, maka peran pemerintah sebagai pemilik saham utama UPI otomatis direduksi,” tegasnya.
Lebih jauh, Elly menyinggung fungsi strategis Menteri dalam penyelesaian konflik internal kampus. Pasal 19 Ayat (3) Statuta UPI menempatkan Menteri sebagai wasit terakhir saat MWA menemui jalan buntu. “Dengan wewenang sebesar itu, bagaimana bisa suaranya dianggap sama?”
Pernyataan Elly menggambarkan kegelisahan mendalam dari kalangan civitas akademika. Mereka khawatir bahwa regulasi baru ini tak hanya mengoyak tatanan hukum, tetapi juga mengikis kemitraan kampus dengan pemerintah.
“Ini bisa menjadi preseden buruk. Bukan tak mungkin, UPI akan bernasib seperti UNS, di mana keputusan pemilihan rektornya dibatalkan kementerian karena cacat prosedural,” tandas Elly.
Kritik ini datang bukan untuk mencederai proses, melainkan menyelamatkannya dari jebakan formalitas yang melupakan esensi. Jika pasal bermasalah ini tak segera direvisi, maka jargon MWA seperti “values for value, full commitment, no conspiracy” hanya akan menjadi sekadar dekorasi kosong di tengah panggung demokrasi yang rapuh.
Sinyal peringatan telah dikirim. Kini, bola panas berada di tangan MWA—akankah mereka mendengar suara akal sehat, atau tetap bertahan dalam keheningan administratif? (*)
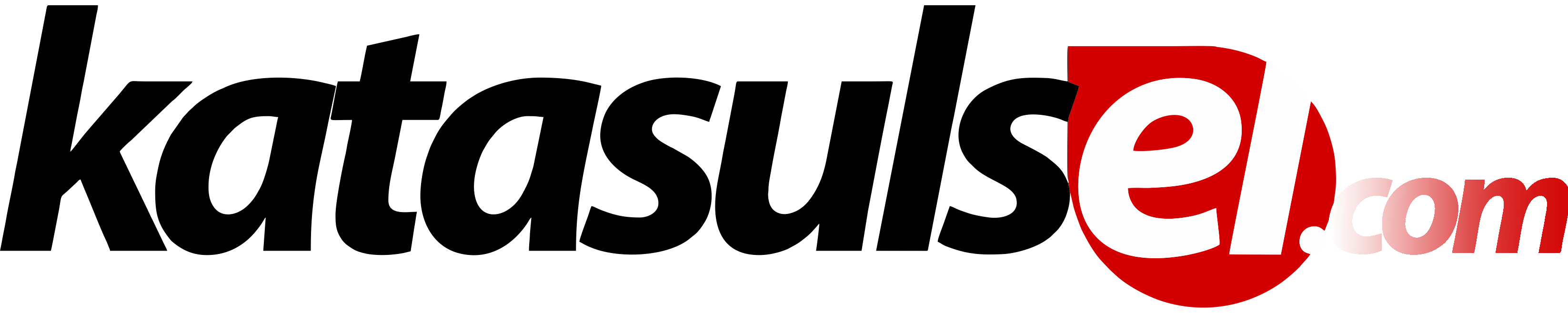













Tinggalkan Balasan