
Di antara riuh nama-nama yang dipanggil satu per satu, ada dua kisah yang menepi dari keramaian — diam, tapi berdetak kencang di dalam dada. Kisah Bapak Aladi dan Ibu Dian di Kota Mataram.
Laporan: Edy Basri
DI SUDUT halaman Kantor Wali Kota, berdiri seorang lelaki dengan rambut yang telah sepenuhnya beruban. Aladi Pristiono, 57 tahun, menyeka pelan keringat di dahinya. Bukan karena panas, tapi karena debar yang sudah ia tahan sejak fajar.
Dua puluh empat tahun, bukan waktu yang sebentar. Ia mengingat betul hari pertama kali mengenakan baju dinas, dua dekade lalu, sebagai tenaga honorer.
Gaji kecil, jam kerja panjang, kadang terlupakan. Tapi tidak sekali pun ia berpikir untuk berhenti. Karena di setiap berkas yang ia layani, ada harga dirinya sebagai seorang pelayan masyarakat.
Hari ini, satu tahun sebelum pensiunnya tiba, Aladi akhirnya diakui negara. Bukan karena ia mengejar gelar, tapi karena ia bertahan saat banyak yang memilih menyerah.
“Saya tidak merasa tua.
Yang saya rasa… masih banyak yang ingin saya berikan,” gumamnya, nyaris pada dirinya sendiri, sambil menggenggam erat Surat Keputusan itu.
Tak jauh darinya, ada perempuan muda yang tak henti-hentinya mengelus perutnya yang besar.
Dian Savitri Utami, 33 tahun, datang dengan langkah perlahan namun pasti. Setiap langkah seakan mengabarkan dua berita bahagia: satu untuk dirinya sendiri, satu lagi untuk kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya.
Pekan depan, dokter menjadwalkan kelahiran bayinya. Tapi hari ini, ia memilih berdiri di bawah panas matahari, menyaksikan sendiri mimpinya yang mekar.
“Waktu seleksi, saya masih mual muntah. Kadang rasanya ingin menyerah, tapi ada dua nyawa yang harus saya perjuangkan — saya dan anak saya,” katanya dengan suara serak menahan haru.
Pelantikan hari itu lebih dari sekadar seremoni. Ia adalah penghargaan diam-diam untuk semua luka yang pernah diabaikan, semua air mata yang pernah ditahan dalam gelap, semua rasa lelah yang tetap dijawab dengan langkah maju.
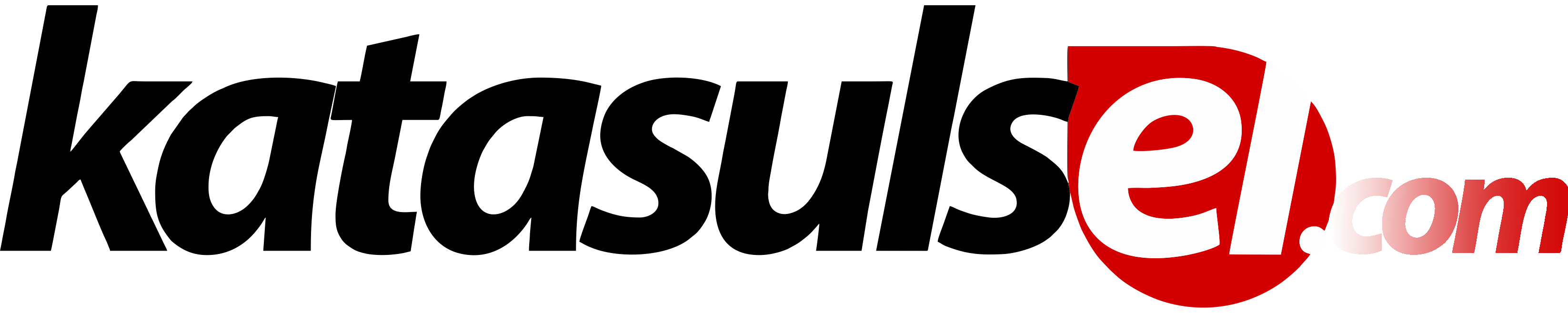







Tinggalkan Balasan