
Refleksi Hari Buruh Internasional
Oleh: Muhammad Idris
Dosen Ilmu Komunikasi FSIKP UMI
Pengurus ISKI Sulawesi Selatan
SEJAK awal tahun 2025, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Tiga sektor yang paling terdampak adalah industri teknologi, manufaktur, dan media massa. Di balik data-data tersebut, ada krisis lain yang tak kalah penting: krisis komunikasi antara pekerja dan perusahaan.
Dalam banyak kasus, PHK tak hanya meninggalkan luka ekonomi bagi pekerja. Yang lebih dalam adalah perasaan tak berdaya karena keputusan yang menyangkut hidup mereka diambil sepihak. Perusahaan sering menyampaikan alasan efisiensi, tekanan inflasi, perlambatan ekonomi, atau melemahnya daya beli. Tapi akar masalah sesungguhnya sering kali adalah kegagalan komunikasi—pekerja diposisikan sebagai objek, bukan lagi subjek dalam proses pengambilan kebijakan.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per Februari 2025, tercatat 18.610 pekerja terkena PHK—melonjak drastis dari Januari yang berjumlah 3.325 orang. Namun, isu penting seperti absennya dialog dalam proses PHK ini kerap luput dari perhatian publik. Informasi tentang PHK pun sering kali disampaikan secara tidak layak: lewat desas-desus, pesan singkat, atau bahkan berita media. Saluran resmi dari manajemen justru jarang digunakan.
Ketimpangan dalam Komunikasi Organisasi
Hubungan antara pekerja dan perusahaan seharusnya dibangun atas dasar mutualisme—saling membutuhkan. Sayangnya, yang terjadi justru komunikasi satu arah. Keputusan PHK dilakukan tanpa ruang dialog. Padahal, menurut prinsip komunikasi organisasi yang adil, opsi PHK mestinya diambil setelah jalan lain seperti pengurangan jam kerja atau program pensiun dini benar-benar tak bisa dijalankan.
Kondisi ini diperparah dengan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja. Upah minimum sering tak sebanding dengan beban kerja, pesangon tidak dibayar sesuai aturan, bahkan banyak yang tak dibayarkan sama sekali. Serikat pekerja, yang seharusnya menjadi pembela, justru tak memiliki kekuatan tawar yang memadai.
Dalam percakapan grup WhatsApp para jurnalis, muncul ungkapan penuh keprihatinan: “Kami seperti pion yang mudah diganti, bahkan dibuang.” Ini bukan sekadar ungkapan emosional, melainkan cerminan ketidakadilan simbolik—sebuah konsep dalam teori komunikasi kritis yang menjelaskan bagaimana pihak lemah dipaksa menerima narasi dominan tanpa ruang untuk menolak atau menegosiasikan.
Program seperti upskilling atau pelatihan pasca-PHK kerap dijadikan alibi oleh perusahaan. Namun tanpa komitmen konkret berupa jaringan kerja atau dana pelatihan, semua itu hanya berhenti sebagai pencitraan.
Membangun Dialog yang Adil
Serikat pekerja, idealnya menjadi jembatan antara pekerja dan manajemen. Namun banyak di antaranya terjebak birokrasi atau bahkan ikut dalam orbit kekuasaan. Karenanya, perlu upaya membangun serikat yang independen dan adaptif—bahkan melalui solidaritas digital seperti petisi online dan kampanye media sosial.
PHK massal sejatinya bukan hanya isu ekonomi, tapi juga isu komunikasi. Transparansi informasi dan kejelasan kriteria PHK harus menjadi kewajiban perusahaan. Dialog harus dihadirkan sebelum keputusan besar diambil. Undang-undang sudah mengamanatkan itu, tinggal bagaimana semua pihak mau menjalankannya.
Pekerja bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Mereka adalah manusia dengan nurani dan harapan, yang bekerja untuk masa depan keluarga dan bangsa. Mereka adalah tulang punggung industri dan ekonomi.
Di Hari Buruh ini, marilah kita tidak hanya merayakan, tapi juga merenungkan pentingnya keadilan komunikasi. Negara, pengusaha, dan pekerja harus duduk bersama dalam ruang dialog yang setara—agar tak ada lagi PHK yang meninggalkan luka dan ketidakadilan.
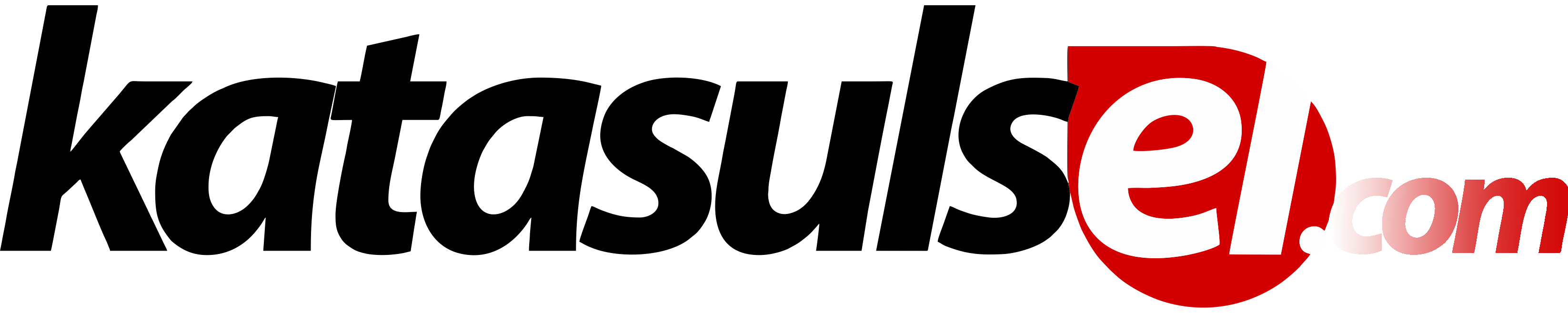








Tinggalkan Balasan